Anggun Prameswari's Blog, page 2
July 15, 2015
Lebaran Damai di Hati Bersama Cermati
Oleh: Anggun Prameswari

Tanggal 1 Syawal begitu dinanti oleh seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di sini, lebaran merupakan asimilasi nilai religi keislaman dan kebudayaan lokal. Selain kekhusyukan ibadah, Lebaran identik dengan kegembiraan dan perayaan. Gaungnya terasa bahkan sebelum datangnya Ramadan. Pekerja yang menunggu libur panjangnya. Keluarga yang menanti waktu berkumpul bersama. Silaturahmi dan saling bermaafan menjadi ritual tak terpisahkan. Lebaranpun menjadi tonggak pengingat agar kita kembali pada fitrah sebagai makhluk sosial; tak lepas dari keluarga dan sahabat.Setiap orang tentu memiliki keinginan di hari lebaran. Baju baru, gawai terkini, mudik ke kampung halaman, berbagi dengan keluarga, atau berlibur. Aku pun begitu. Beberapa bulan sebelum Lebaran, aku telah menyusun #ResolusiLebaranku. Tentu saja, #ResolusiLebaranku membutuhkan dana besar. Untungnya aku—seperti kebanyakan pekerja di Indonesia--menerima THR untuk merayakan hari raya. Sekilas, THR seperti rejeki nomplok. Mendapat uang di luar gaji bulanan, ditambah tren diskon dan promo Lebaran, rasanya ingin langsung saja menghabiskan uang di tangan. Namun, belajar dari pengalaman, serta curhatan keluarga dan sahabat, THR akan menguap sia-sia jika tidak dikelola dengan baik. THR bukan uang jatuh dari langit yang bisa dihamburkan tanpa rencana. THR bersifat bantuan antisipatif, baik buruknya, tergantung bagaimana mengaturnya.Sebagai generasi melek internet, akupun browsingmencari tip pengaturan THR. Beruntung kutemukan situs Cermati.Com! Sesuai dengan tagline-nya, Mari Jadikan Orang Indonesia Cermat Berfinansial, Cermati membantuku memperoleh wawasan lebih luas mengenai produk-produk perbankan sekaligus tip-tip mengatur keuangan. Bahkan dari salah satu artikel Cermati, aku disarankan membagi alokasi THR ke dalam beberapa pos dengan presentase tertentu.Spesial tahun ini, #ResolusiLebaranku adalah:1. Beramal untuk sesama, 2. Alokasi mudik, dan 3. Menambah dana darurat. Langkah pertama, aku perlu mengetahui besaran THR yang kuterima, agar bisa membuat perencanaan. Ini bisa kuketahui dari jumlah gaji pokok atau prediksi THR tahun sebelumnya. Karena THR biasanya cair seminggu menjelang lebaran, kugunakan tabungan dana darurat untuk menalangi semua kebutuhan, yang nanti ditutup kembali dengan THR setelah cair.Sejak kecil, orangtuaku mengajarkan untuk beramal—sedikit banyak rejeki yang kita terima. Aku ingat bagaimana orangtuaku mengajariku di setiap Rupiah yang kita punya ada 2,5% hak orang lain yang lebih membutuhkan. Selain dengan lisan, orangtuaku menunjukkannya dengan perbuatan, sehingga nilai itu begitu meresap di hati. Oleh karena itu, pos prioritas THR adalah zakat fitrah, zakat penghasilan, serta THR orang-orang yang bekerja membantu kita, misalnya asisten rumah tangga. Diperkirakan pos ini akan memakan 15% dari total THR. Untuk mempermudah pembagiannya, kuterapkan sistem amplop. Aku membuat pemetaan asumsi nominal untuk pos-pos tersebut, lalu memasukkan uangnya ke dalam amplop. Cara ini mempermudahkanku mengendalikan cash flow. #ResolusiLebaranku berikutnya adalah mudik ke kampung halaman. Sebagai anak rantau, mudik merupakan momen dinanti untuk berkumpul bersama.Untuk pos ini, aku mengatur maksimal 60% dari total THR. Sayangnya, harga tiket yang melambung tinggi pada arus mudik dan arus balik, membuatku kesulitan mengatur alokasi dana mudik. Kusiasati dengan memesan tiket pesawat 2-3 bulan sebelum tanggal keberangkatan. Kugunakan kartu kredit untuk membelinya secara online sebelum THR turun. Beruntung, aku bisa memperoleh tiket dengan harga di bawah perkiraan. Selain tiket lebaran, budgetangpau kepada keponakan, hantaran untuk keluarga, baju baru, dan keperluan lebaran lainnya masuk pada pos ini. Apabila over-budget, ada solusi menggunakan tabungan dana darurat atau gadai barang. Dengan begini, aku tidak perlu memiliki utang tambahan setelah lebaran selesai.Nah, sisa 25%-nya bisa dipecah menjadi dua bagian, yaitu membayar utang (15%) dan menambah dana investasi (10%). Untungnya, tahun ini aku tidak memiliki utang. Bahkan tagihan Kartu Kredit untuk membeli tiket masih jadi bagian dana mudik yang 60% tadi. Sisa dana 25% ini bisa langsung dialokasikan untuk investasi. Kali ini aku berencana untuk menambah nominal dana darurat, yang merupakan #ResolusiLebaranku yang ketiga. Kerennya, situs Cermati memberikan informasi perbandingan produk-produk perbankan, mulai dari tabungan, deposito, kartu kredit, sampai aneka kredit. Aku jadi tahu deposito dan tabungan mana yang memberikan bunga maksimal sehingga investasiku terus berkembang. Ada juga info aneka kredit, di mana tersedia info rate bunga, persyaratan, dan simulasi lengkap dari beragam bank di Indonesia. Data di situs Cermati sangat membantuku membuat keputusan finansial. Makanya saat kumpul keluarga, aku tak segan bercerita pada keluarga dan sahabat mengenai fitur di Cermati. Sepupuku yang berencana mengambil KPR, adikku yang hendak membeli mobil, dan Budhe yang tengah bingung hendak membuka deposito di mana, semuanya jadi tahu. Mudah sekali, hanya tinggal klik situs www.cermati.com dan segala informasi tersaji di sana. Situs ini nyaman diakses secara mobile sehingga praktis. Memutuskan produk perbankan mana yang dipilih menjadi lebih mudah dan aman.Lebaran kali ini, aku bersyukur #ResolusiLebaranku tercapai karena pengaturan yang cermat. Selain itu, aku belajar bahwa berbagi itu indah. Dengan berbagi, hati kita menjadi lebih kaya dan bahagia. Dari Cermati pula, aku sadar bahwa berbagi tak hanya dengan uang. Ilmu dan informasi menjadi tak kalah berharganya, untuk dibagi kepada sesama.
Tulisan ini merupakan bagian lomba blog #ResolusiLebaranku bersama situs keuangan www.cermati.com
[image error]
Published on July 15, 2015 01:13
April 20, 2015
[CERPEN] Linuwih Aroma Jarik Baru

Muat di Harian Kompas, Minggu, 19 April 2015Ilustrasi Cerpen oleh Yusuf Susilo Hartono
Kaulah perempuan itu; perempuan yang bangun dari kematian. Entah untung atau buntung, Tuhan mengembalikan ruhmu tak lama setelah mencabutnya paksa; seperti menyentak gulma dari tanah, lalu menjejalkannya kembali sedemikian rupa.Seminggu sebelum kejadian itu, kau tengah berladang di sawah ibumu yang cuma sepetak. Hujan deras membuatmu kuyup. Karena awalnya memang kau tak sehat betul, hawa dingin dengan cepat membuat badanmu membara setiba di rumah. Bergelung jarik, kau mengigau tak keruan. Segala obat kau telan, tetap sia-sia. Tepat di malam purnama, hari ketujuh demammu, tiba-tiba tanganmu terulur ke udara, seakan menahan sesuatu. Apakah malaikat datang merenggut paksa jiwamu, tapi kau teguh memperjuangkannya?Samar kau ingat, air mata ibumu luruh saat melihatmu meregang nyawa. Tangisnya menyayat ke seluruh penjuru dusun. Tetangga berdatangan. Sebagian besar karena tak tega mendengar isak ibumu yang mendadak sebatang kara. Tubuhmu disemayamkan berselimut jarik baru bermotif kawung yang aroma lilinnya belum luntur. Doa para tamu dan tangis ibumu bersahut-sahutan; tak ada yang mau kalah.Lalu, di antara riuh itu, menyeruaklah suara batuk-batuk. Pertama lirih, lama-lama melantang. Tahu-tahu kau bangkit, membuat jantung mereka setengah terlontar lepas. Mulut-mulut menganga, persis ikan-ikan yang menggelepar. Kau yang bangun-bangun bingung—masih pening oleh aroma kain penutup jenazah—ditubruk peluk limbung ibumu.Sejak itu kau memiliki linuwih. Kemampuan ”lebih” tiba-tiba dijatuhkan begitu saja dari langit. Kau bisa tahu siapa saja yang dijemput ajal. Pertanda itu menghampirimu dalam bentuk aroma jarik baru, yang bau lilinnya masih pekat. Persis bau pertama yang kau cium setelah bangun dari matimu. Awalnya samar serupa liukan tangan penari yang menuntunmu ke atas panggung. Mau tak mau kau mengikutinya. Jika aroma itu makin kuat, maka makin dekatlah kau pada si calon mayat.Maka selelah atau sesibuk apapun, bila aroma jarik baru mendatangimu, kau akan mencari sumbernya dan mengunjunginya untuk tanda penghormatan. Bukankah itu inti hidup? Perjalanan demi pencarian yang mengantar pada kepulangan sesungguhnya?Hanya ibu yang tahu linuwih ini. Padanya kau memberanikan diri bertanya kenapa kau dilimpahi linuwih aroma jarik baru. Kelak akan ada satu kematian yang mengajarimu makna linuwih itu sendiri, begitu katanya sambil melipat kain jarik yang baru dicuci.Ah, jarik selalu identik dengan ibu. Kain batik selalu membungkus tubuh mungilnya yang mirip ranting; berkali-kali meliuk ditiup angin, tapi tak kunjung patah.Suatu kali kau menjulurkan kepala di ambang kamar ibu. Wanita itu bersimpuh. Hening dan tenang, tangannya mewiru selembar jarik. Dilipat-lipatnya pinggiran kain dengan telaten, rapi bertumpuk sama lebar. Garis putih pada ujungnya tak ditekuk ke dalam.”Temani ibu ngawiron jarik dari bapak. Cium bau malamnya, masih baru.” Ibu mengangsurkan kain itu padamu.Kau menghirup pekat aroma lilin. Kaubayangkan wajah bapak, tapi gagal. Bagaimana bisa mengingat orang yang kepulangannya nyenyai?”Ngawiron iku aja nganti kleru. Lipatannya harus sama. Jangan sampai keliru, apalagi merusak keseimbangan. Hidup tidak akan harmonis dan bahagia.”Kau membatin, apa ibu bahagia? Selembar kain batik dari bapak apa cukup mengisi kekosongan besar di hati ibu yang terlalu lama ditinggalkan? Bagimu, tidak.”Jarik selalu ada dalam siklus hidup orang Jawa,” papar ibumu tanpa diminta. ”Alas tidur bayi, gendongan, kain basahan untuk mandi, semuanya memakai jarik. Menikah nanti, kamu dan suamimu akan berkain jarik. Bahkan ketika meninggal, jarik kawung akan menyelimutimu kembali ke alam suwung.”Ada yang membuatmu pilu saat ibu menyebutkan kata suami. Namun kau belajar menyimpan gundah, karena itulah dada perempuan diciptakan. Ibu pun melanjutkan mewiru jarik, yang kau ketahui di kemudian hari, dikenakan ibu di pesta pernikahan bapakmu dengan istri mudanya.”Kamu tahu kenapa bapak menghadiahi jarik ini?” bisik ibu di tengah kerumunan tamu bapak. ”Jarik artinya aja gampang serik. Mengingatkan ibu tidak boleh iri pada apa-apa yang bukan milik.”Tersembul getir di nada ibu. Hatimu ikut teriris. Sepasang matamu merekam ibu yang berbalut jarik melangkah hati-hati, tanpa terburu; menghampiri kedua pengantin.Begitukah keinginan bapak terhadap jalan hidup kalian? Tidak iri dan berjalan lambat menghayati tiap ketentuan yang dipilihkan, tanpa bisa menggugat?Dan di sanalah kau mencium aroma itu. Pekat lilin baru di lembar kain mori. Samar awalnya, kemudian menguat di tiap langkahmu mendekat ke pelaminan bapak.Kau tahu apa yang akan terjadi. Namun, kau memilih diam. Bahkan ketika lelaki itu harus tewas di atas pelaminan, ditancap perutnya berkali-kali oleh belati, karena amuk pemuda yang geram kekasihnya dinikahi bapak, kau bergeming. Bukankah itu yang dia telah tanamkan di hatimu dan ibu? Kepasrahan.Termasuk pasrah menghayati tangis ibu; berkelindan dengan ruap aroma jarik baru yang perlahan memudar.Ketika pagi itu kau menghirup aroma yang sama, ada rasa tak enak yang luar biasa. Tak pernah sebelumnya, rasa takut menderamu seperti itu. Kau menuju dapur, berusaha menenangkan diri dengan segelas air.Betapa rusuh benak dan isi dadamu; aroma jarik baru itu menguat saat ibu melintas di depanmu. Nyaris saja gelas di tangan meluncur jatuh, persis jantungmu yang mencelus.”Kau seperti baru melihat hantu,” ujar ibu berlalu menuju kamar.Dua gelas air habis kau teguk untuk menutupi kebohongan. Dalam kepalamu, segala bayang buruk berlesatan. Apa kau sanggup hidup membayangkan hidup tanpa ibu? Sungguh, sepanjang kau memiliki linuwih ini, tak sekali pun terpikirkan ini.Tak tahan lagi, kau terobos pintu bilik kamar ibu. Wanita itu menegakkan tubuh, menjauh dari tumpukan jarik yang tengah dirapikan.”Mari ke kota, Bu. Membeli jarik baru,” begitu katamu tiba-tiba. ”Ada sedikit uang. Aku ingin memberi ibu hadiah.”Sejenak mata sayu ibu mencoba membacamu. Jantungmu berderap, siap merancang kebohongan lainnya. Namun, ibu mengiyakan dan menyuruhmu menunggunya berganti baju.Jarik terbaik dikenakannya. Rambutnya digelung rapi. Tak ada gincu atau bedak berlebihan. Dari rumah, kalian menyusuri setapak menuju jalan besar. Tak jauh dari sana ada perempatan dengan pos menunggu mobil angkutan menuju kota. Tak sedetik pun tangan ibu lepas menggamit lenganmu. Dadamu sesak. Udara yang kau hirup beraroma tajam, mengiris hatimu lamat-lamat.Ada keakraban yang tiba-tiba muncul. Sepanjang perjalanan, ibu bercerita banyak, termasuk bagaimana kau dulu nyaris tak berhasil dilahirkan.”Ibu sudah ikhlas, tapi ibu tetap berjuang.”Hatimu menghangat mendengarnya.”Persis ketika kamu sempat mati. Ibu ikhlas.”Namun jika hal itu dibalik, kau tak yakin apa juga bisa ikhlas.”Yang sudah ditulis takdir, tak mungkin dicurangi.”Kau curiga ibu mengintip isi pikiranmu. Selanjutnya, ibu tak berkata apa-apa lagi. Kalian hanya diam sampai angkutan berhenti di depan pasar. Di sebuah kios, seorang emak tambun berwajah lembap keringat dan bertangan kemerincing gelang emas sepuhan menyambut kalian. Ibumu meminta diambilkan selembar batik kawung. Hatimu langsung terjun bebas.Emak tambun itu membentangkan lembar batik motif kawung. Tak lagi bisa kau bedakan aroma linuwih atau kain pilihan ibu. Dominan hitam dan coklat tua membuat pandanganmu sekejap menggelap. Bentuk-bentuk lonjong sama besar dengan garis bersinggungan, mengingatkanmu pada lengkung kolang-kaling dengan motif serupa keping uang sen kuno. Batik kawung memang terkenal sebagai lurup—kau ingat dulu kain inilah yang menutupi jasadmu.”Yang ini saja,” ujarnya mantap.Kau tersenyum sekenanya, menutupi rasa gamam di dada. Ibu selalu tahu gundah apa di hatimu, binar riang di matamu, bahkan hela napasmu yang mendadak lain. Kau adalah buku yang tak pernah gagal dibaca ibu. Namun, pernahkah kau bertanya, kematian seperti apa yang diinginkan ibu?”Kenapa jarik kawung, Bu?””Apa seharusnya ibu pilih truntum atau sidomukti? Memangnya sudah ada yang melamarmu?”Seharusnya pipimu memerah. Mestinya kau salah tingkah. Namun, kau makin susah bernapas. Udara di sekelilingmu dipenuhi aroma, yang untuk pertama kalinya sejak memiliki linuwih itu, sangat kau benci.”Bayarlah, lalu kita pulang,” ujar ibu.Kata terakhir itu membuatmu bergidik. Pulang ke mana? Tentu saja ke rumah yang telah kalian huni bertahun-tahun. Bukan menuju keabadian.Saat menunggu angkutan ke dusun, di depanmu ada selembar daun tertiup angin. Kau genggam tangan ibu kuat-kuat. Kau takut ibu seperti daun itu; tahu-tahu terbawa pergi.Saat angkutan menghampiri, kau hitung detik yang tersisa. Sembari mendekap bungkusan berisi batik kawung itu, ibu memiringkan kepala menyuruhmu lekas naik.”Ayo pulang,” ujar ibu tersenyum, seakan tahu segala rahasia yang berimpitan di kepalamu.Walau ragu, tetap saja kau naik. Kau pejamkan mata sambil terus menggenggam tangan ibu. Iya, Bu. Kita pulang sekarang. Mobil itu melaju, sesekali berguncang melintasi jalan bergelombang. Di luar, kau lihat langit menggelap. Seakan apa yang kau punya di dada, tertular ke semesta. Kau menatap wajah ibu sekali lagi. Matanya terpejam, damai sekali. Mungkin bungkusan jarik barunya memberikan ketenangan. Kau makin takut, kalau-kalau mata itu tak terbuka lagi.Langit pecah jadi hujan. Jalan basah makin rawan. Saat mobil berbelok di tikungan tajam, kau hendak mengingatkan sopir untuk hati-hati. Lelaki tua bertopi lebar dan berkalung handuk itu menoleh sekilas. Namun, kau takkan lupa sorot di sudut matanya. Kelam dan kosong. Kalian pernah jumpa, kau bisa merasakan itu. Mengingatkanmu pada hening alam suwung yang pernah kau kunjungi, di suatu masa.Kembali kau disergap sesuatu. Aroma itu.Tunggu! Ya, aku juga menciumnya. Bau lilin batik di kain yang masih baru. Makin lama makin kuat…
Published on April 20, 2015 00:06
March 28, 2015
[CERPEN] - Kembang Pulang
Jika ada yang bertanya mana yang lebih dingin, udara malam atau hawa hatinya, Ros akan meraba dadanya. Ada gunung es tumbuh di sana. Sekarang pukul tiga dini hari. Yu Jum terkantuk-kantuk di meja kasir. Pendar papan iklan bir berneon merah-hijau di beranda wisma, tengah meregang kelip terakhir sebelum benar-benar padam. Tamu kelimanya di hari ini baru pulang dengan langkah terseok, setengah mabuk. Ros keburu lupa wajah tamunya itu. Baginya, lelaki selalu tak lebih dari sosok tak berwajah.Termasuk lelaki itu, yang seharusnya dihukum karena telah mendinginkan dadanya. Dari cerita masa kecilnya, lelaki itu suka sekali pada rumpun kembang ros yang berayun-ayun di bawah jendela kamar tidur ibunya. Masih nunggu tamu, Ros? Yu Jum menaikkan resleting jaketnya tinggi-tinggi. Kejar setoran ya. Jangan lupa, sisakan buat yang lain.Tak mengacuhkan Yu Jum, matanya menatap neonbox sebuah merk bir. Suaranya terdengar berderak-derak nyaris padam. Angin menjelang fajar semakin kejam. Jalanan di depan pintu wisma mulai sepi. Denting penggorengan tukang tahu tek beradu dengan sayup musik dangdut. Bahkan di masa seharusnya dunia terlelap, kehidupan masih berdenyut. Kalau hatinya sudah sedingin ini, biasanya Ros berlari ke pinggir jalan dan menatap ujungnya. Ada harap yang menggelembung, kalau-kalau lelaki itu––ayahnya––pulang.Ke mana ayah? Kapan pulang?Kenapa ayah pergi tidak mengajak kita?Ros kecil yang cerewet. Kata orang-orang dulu, bibir Ros serupa butir anggur ranum, menggemaskan. Kata orang-orang kini, bibir Ros layak disebut berpulas anggur merah, memabukkan. Bibir itu Ros warisi dari ibu, yang sepanjang ingatannya pula, tak pernah ia dapati bibir itu banyak berbicara.Tak sekalipun Ros tahu apa ayahnya kurus atau tambun. Berkumis atau berjenggot. Beraroma kretek atau wangi parfum murahan. Yang ia tahu, ayah tak pernah. Kadang Ros berharap ibu sama cerewetnya seperti Yu Jum, yang selalu mengurusi hidup orang hingga ia tak perlu meraba sosok ayahnya dalam sosok lelaki yang berganti lebih cepat dari guguran daun meranggas.Minggu depan wisma tutup, Ros, Yu Jum menyalakan rokoknya. Dapat uang kamu nanti. Tiga juta.Derak tembakau di kiri Ros beradu dengan pendar neon box yang menyedihkan. Yu Jum ikut-ikutan menatap ke arah yang sama.Apa rencanamu, Ros?Pulang, Yu.Ke mana? Memangnya punya rumah untuk pulang?Ros diam.Gang ini mau disapu, Ros. Biar bersih, katanya. Memangnya kita sampah ya, Ros? Padahal mereka menyebut kita perempuan harapan, yang masih bisa hidup lebih baik walau ditukar dengan uang tiga juta, asap embusan rokok Yu Jum melayang-layang lebih jauh. Kasihan papi-papimu nanti, Ros. Pasti mereka kangen kamu.Dada Ros makin dingin. Entah berapa lelaki yang ia senangkan, tapi tak sebanding untuk menambal lubang di dadanya. Tak ada ayah yang bermain ayunan bersama, mengantarkannya ke sekolah, menepuk manja kepalanya. Menyelimutinya saat demam, memarahinya saat pulang pacaran terlalu malam. Mungkin karena itu Ros lebih suka tamu lelaki yang lebih tua, yang sebenarnya lebih pantas ia sebut ayah. Seluruh penghuni wisma maklum itu. Mereka selalu menyodorkan lelaki setengah baya ke pangkuan Ros untuk disenangkan, berharap Ros juga bisa menyenangkan hatinya sendiri.Tiap ada lelaki masuk ke wisma, melewati pintu yang dinaungi neon box bir itu, asa di dadanya menyerupai balon. Mengembang besar. Namun, Ros belajar sejak lama tentang cara lelaki menatap dirinya. Mereka yang datang tak pernah menatapnya penuh rindu, sebagaimana dirinya merindukan ayah. Ia hanya dianggap kembang, untuk dihirup wanginya, menghias sepi, lalu ditinggalkan bila waktunya tiba. Dingin di dadanya menjadi-jadi. Ros tinggal menunggu hari di mana hatinya benar-benar mati. Persis wisma ini. Mirip neon box itu.Aku pengin ketemu ayah, Yu.Di mana dia? Ayahmu bahkan sudah pergi sebelum ibumu tahu dirinya hamil. Kamu lahir di sini, besar di sini, cari makan juga di sini. Gang ini boleh disapu, Ros, tapi ini kampungmu. Ibumu dulu kembang di sini. Sekarang kamu juga. Buat kita, inilah rumah. Mau ngapain ketemu lelaki itu lagi?Ada skenario di kepalanya kalau ia bertemu ayah. Pertama, ia akan marah sebesar-besarnya. Bagaimana bisa ayah sekejam itu, meninggalkan anak perempuannya seorang diri, tanpa membekali pengetahuan tentang hidup. Bagaimana caranya naik sepeda. Bagaimana mengerjakan PR matematika. Bagaimana menghadapi teman sekolah yang centil. Bagaimana membedakan laki-laki yang benar-benar baik dari sekian banyak lelaki yang tampak baik. Lalu ia akan menangis. Air matanya berjatuhan persis hujan di Desember. Segala momen yang hilang akan ia tangisi. Bukankah lelaki lemah pada air mata wanita? Ayah akan semakin sedih hatinya, lalu memeluknya. Maka, gunung es di dadanya akan pelan mencair, sehingga airmatanya menjadi air bah yang menenggelamkan mereka berdua. Selanjutnya, Ros akan bercerita. Tentang luka di lututnya karena terjatuh saat belajar sepeda sendiri. Tentang pacar pertama yang diam-diam menciumnya di atas becak selepas nonton dangdut di kampung sebelah. Tentang ibu yang tak pernah berhenti menangis tiap tengah malam. Tentang sulitnya hidup perempuan yang bertahan seorang diri. Tentang lembar rupiah yang cepat menguap entah menjadi apa. Tentang tamu pertama yang menaiki tubuhnya, dengan dengus napas seperti kerbau mengamuk, tapi tak juga Ros bisa ingat seperti apa wajahnya. Tentang dingin di dadanya, yang tak bisa dihangatkan oleh lelaki yang silih berganti menghangatkan ranjangnya di wisma.Sampai tiba akhirnya Ros memaafkannya, karena toh ia telanjur mencintai ayahnya. Bukankah cinta pertama seorang perempuan adalah ayahnya, dan konon cinta pertama itu takkan mati?Kalau wisma ini tutup, kita bagaimana ya Ros?Ya pindah. Pulang ke kampung, buka warung atau apalah. Ngomongmu sudah seperti Walikota saja. Ros membalikkan badan. Tubuhnya mendadak begitu lelah. Sendi-sendinya mulai berlepasan, entah karena tamu terakhir membolak-balik tubuhnya seperti adonan panekuk setengah matang atau karena tak ada lagi tenaga untuk berpikir. Derak neon box itu kini lebih cepat, tapi sekaligus melemah. Pulang, Yu. Aku pengin pulang.Pet! Mata Yu Jum dan Ros bertautan tepat saat neon box itu padam, seakan menandai usainya kehidupan di sebuah lekuk jalanan yang disesaki wisma-wisma penuh kembang yang wangi, yang tinggal menunggu hari untuk hilang.***Ros menutup berkasnya sembari menghela napas. Setengah mati dia berusaha mengabaikan sorot mata dari ujung ruang tunggu. Padahal dia sudah berpakaian teramat sopan. Kemeja lengan panjang dan pantalon hitam. Pagi tadi dia malah menghabiskan setengah jam hanya untuk memutuskan apakah rambutnya diurai atau digelung. Mana yang terlihat tak terlalu “mengundang”. Namun, prasangka buruk memang selalu lebih mudah dilakukan.Mantan “itu” ya?Nyari dana katanya. Buat LSM tempatnya sekarang kerja.Sekalian jualan?Ngawur!Sayang sekali, padahal cantik.Jangan-jangan masih terima order.Kalau sama aku, dia mau nggak ya?Wani piro kowe, Mas, hahaha?Pagi tadi, sebelum Ros tiba di kantor institusi swasta yang konon mengajaknya meeting untuk urusan pendanaan, Ros melewati gang itu. Jalanan di sana tak lagi sama ramainya. Lokalisasi itu memang resmi ditutup. Gang yang dulu begitu hidup kini mati. Kembang-kembang yang dulu tumbuh merekah, dicabut paksa kemudian mati. Atau tertatih-tatih mencari tanah, untuk kembali menancapkan akar di tanah lain yang masih sudi menerimanya. “Mbak Ros ini mantan penghuni gang ya? Sekarang kerja di LSM pemberdayaan perempuan?” tanya pimpinan itu dengan sorot menyelidik. Tadinya Ros kira, begitu masuk ruang pimpinan, dia terbebas dari tatapan menghakimi di ruang tunggu. Sayangnya tidak. Ros menggenggam tangannya erat-erat. “Iya. Saya ditawari kerja di sana.”“Kalau mantan penghuni lainnya, pada ke mana, Mbak?”“Ada yang pulang ke keluarganya, membuka usaha, pergi ke kota lain, dan ada juga yang meneruskan profesi lama diam-diam.”“Wah, percuma dong lokalisasinya ditutup.”“Oleh karenanya, LSM kami membantu mengedukasi mereka, terutama kesehatan seksual dan kemandirian ekonomi. Bantuan dana dari perusahaan bapak sangat berarti.”“Angkanya besar juga ya,” pria itu mengalihkan pandangan dari berkas proposal ke arah Ros. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. “Bisa dong kita bahas ini di tempat yang lebih privat. Kamu tahulah maksud saya.”Ros hapal betul itu. Raut wajah lelaki yang mencari persinggahan, bukan rumah untuk pulang. Dadanya memanas. Kembali menggelegak kenangan tentang ayah yang asing, tentang ibu yang mati pelan-pelan oleh kesedihan, tentang kembang-kembang lain yang dicerabut paksa tanpa bisa dicarikan tempat untuk tumbuh merekah indah, tanpa dipandang sebelah mata.Dia perempuan. Mereka perempuan. Apa begitu sulit menjadikan perempuan sebagai rumah untuk pulang, bukan hanya tempat persinggahan. Bahkan ketika Ros mencoba jalan yang berbeda, orang-orang di sekelilingnya terus kembali mendorongnya kembali ke taman yang sama. Taman yang mereka anggap cocok untuk kembang seperti dirinya.Termasuk pesan pendek dari Yu Jum tadi pagi.Sudah ketemu ayahmu? Kujamin belum. Nggak usah mimpi-mimpi tentang ayahmu atau hidup benar. Ayo balik. Tak ada ayah, papi pun jadi. Telepon aku, nanti kukasih tahu alamat hotelnya.“Bagaimana, Mbak Ros?” tanya lelaki itu sekali lagi.Ros merasakan dadanya ditumbuhi gunung es. Lebih besar. Makin kokoh. Yang terbayang di matanya hanya pendar neon boxsebuah merk bir yang sekarat, nyaris mati. Mengingatkannya pada diri sendiriRos langsung menarik kembali berkas proposal, dengan sekali sentakan paksa. Wajah pimpinan itu memerah, nyaris meletus oleh penolakannya. Ros tak menoleh ke belakang. Sudah lama dia menyerah akan masa lalu yang lebih sulit dihapus ketimbang sebuah tato atau tanda lahir. Apapun yang dia lakukan, mereka akan selalu memandangnya sama.Maka, kalau Ros tak bisa menemukan rumahnya untuk pulang, maka biar dia yang membangunnya sendiri.[]
Catatan: Karena miskomunikasi, cerpen ini dimuat ganda di majalah Femina no.12/XLIII (edar 21-27 Maret 2015) dan tabloid Nova no.1412/XXVIII (edar 16-22 Maret 2015). Bukan sesuatu yang membanggakan karena pemuatan ganda adalah kesalahan besar. Masalah pemuatan ganda ini sudah selesai antara aku dan kedua media yang bersangkutan. Lihatlah dari sisi positifnya. Lebih banyak orang yang membaca cerpen ini. Semoga bermanfaat.
Published on March 28, 2015 05:43
March 27, 2015
[CERPEN] - Papa Untuk Anakku
 Dimuat di Majalah Good Housekeeping edisi November 2014 Tanganku ragu membuka pintu berhiaskan poster Ben 10 itu dan hiasan gantung kayu bertulis Nizam’s Room. Kuusap wajahku beberapa kali sampai tak ada air mata tersisa lagi. Kupasang senyum terbaik yang kupunya. Kusuguhkan hanya wajah bahagia padanya.“Belum bobo, sayang?” sapaku.Nizam menatapku dari balik selimut. Binar sepasang mata, senyum yang merekah, dan uluran tangan memohon pelukan, semuanya kurekam erat-erat. Itulah pemandangan yang mengusir semua lelah dan menyirami hatiku dengan asa. Nizamlah yang membuat hidupku jauh lebih berharga sepeninggal mantan suamiku. “Bunda kok baru pulang jam segini?”“Maaf ya. Kamu nungguin Bunda?”Nizam mengangguk cepat beberapa kali. Pipi gembilnya naik turun mengikuti irama kepala. Langsung kupeluk dia dan kuserang dengan ciuman bertubi-tubi di seluruh wajahnya. Nizam terkekeh kegelian dan meronta-ronta. Kuhirup habis wangi tubuhnya seperti pecandu yang mengisap bakaran daun kanabis. “Bunda diantar sama Om Denis?” tanya Nizam polos. Sejenak aku menatapnya sembari menimbang apakah harus mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Jujur saja. Aku pun mengangguk cepat.“Kenapa Om Denis nggak mampir ke kamar Nizam dan bacakan dongeng?”“Om Denis harus buru-buru pulang. Sudah malam, kan?” aku melirik ke arah jam dinding. Jam sembilan lebih sedikit.“Bun, kapan Om Denis jadi papa Nizam?” ujarnya tiba-tiba. Pandangannya mengunci mataku. Sorot itu mampu membendung niatku untuk berbohong. Aku tak sanggup mendustai sepasang mata malaikat di depanku.“Teman-teman Nizam di sekolah bilang Bunda akan menikah sama Om Denis. Nizam akan punya papa baru. Kapan, Bun? Masih lama ya?”Sepasang mata itu langsung menyayat hatiku. Aku langsung memeluknya. Diam-diam air mataku merembes perlahan.“Nizam mau punya papa sebaik Om Denis, Bun. Cepat nikah ya, biar Om Denis bisa pindah kemari. Jadi Bunda sama Nizam nggak kesepian lagi.”Sekuat apa pun aku menahan suara, isakan itu sanggup menyelinap keluar dari bibirku. Air mataku semakin deras mengalir. Kupeluk Nizam makin erat. Bocah lima tahun itu sedikit meronta, tapi ia seakan paham, akhirnya memilih diam.“Bunda, kenapa nangis? Nizam nakal, ya?” tanyanya sambil mengelus punggungku.Tenggorokanku tercekat. Tak ada kata yang keluar. Seharusnya padakulah Nizam mencari ketenangan. Namun, aku seakan mencari kekuatan pada pelukan rapuh ini. Nizam terus mengelus punggungku. Kubiarkan malam yang makin tua di sana membawa bayang-bayang Denis menjauh. Biarkan aku berbagi hangat sejenak di ranjang Nizam.“Cup cup, Bunda, jangan nangis ya. Cup cup,” ujar Nizam polos.***Parsel buah di tanganku bergetar hebat. Tanpa banyak bicara, Denis mengambilnya dariku dengan satu tangan, lalu tangan lainnya menggenggam tanganku. Bisa kurasakan perbedaan kedua kulit kami. Tangannya besar dan hangat. Seperti selimut, tangan itu menangkup penuh pada tangan mungilku yang dingin. Ia pasti bisa menyadari badai yang bergemuruh di dadaku.“Operasi jantung ibu berhasil. Ibu akan baik-baik saja,” hiburnya. Siapa yang tengah dia hibur? Dirinya sendirikah lantaran sang ibu akhirnya lolos dari maut? Atau menghiburku yang sejak beberapa hari lalu tenggelam dari rasa bersalah?“Kamu yakin sakit jantung ibu nggak akan kambuh kalau melihatku?”“Tadinya kupikir begitu. Tapi ibu sendiri yang ingin ketemu kamu.”Aku menghela napas perlahan. Ini di luar dugaan. Ibu akhirnya mau menemuiku setelah drama panjang kami beberapa waktu lalu. Aku tak bisa menebak apa yang ada di kepala ibu.“Ibumu nggak pernah suka sama aku,” jawabku lirih.“Ibu cuma belum kenal sama kamu. Selama ini aku coba bujuk ibu. Mungkin setelah operasi itu, pikiran ibu jadi lebih terbuka. Siapa tahu ibu merestui kita?”“Ibu mana yang rela anak bujangnya menikah sama janda cerai beranak satu?” Denis tersentak menolehku. Ting!Denting lift terbuka dan percakapan kami berhenti sampai di sana. Sejenak aku ragu keluar dari sana untuk bertemu ibunya. Namun, tangannya menarik pelan. Seakan-akan hangatnya enggan melepasku pergi. Ibu duduk di kursi roda. Perawat tengah membawanya berjalan-jalan ke taman rumah sakit. Duduknya tenang dengan tiang infus menjulang di belakang. Wajahnya nampak segar. Mungkin darah sudah mengalir sempurna di tubuhnya berkat operasi itu. Namun tetap saja, tak ada senyum yang menyambutku. Hatiku langsung dicengkeram perasaan dingin. Kami semua sejenak memandangi pepohonan dan air mancur dalam diam. Kulirik ibu. Wajahnya tenang, sesekali terpejam. Tak ada tanda beliau akan menyerangku dengan kata-kata pedasnya seperti terakhir kami bertemu.“Den, tolong belikan ibu air putih. Kamu juga mau?” tawarnya padaku. Aku tersentak kaget dan menggeleng cepat. Denis sedikit ragu, tapi aku tersenyum. Kuyakinkan kalau kami berdua akan baik-baik saja di sini, walau sebenarnya diriku sendiri meragukannya.Aku melihat punggung Denis yang menjauh. Ada keheningan yang tumbuh di antara aku dan sang ibu. Aku memberanikan diri menatapnya. “Kamu masih ingat terakhir kita ketemu?” tanya ibu seakan tahu aku tengah mengamatinya. Aku mengangguk. “Denis bilang sama ibu kalau dia mau nikah sama kamu.”Kata-kata itu membawaku kembali pada pertemuan minggu lalu. Aku, Denis, dan sang ibu duduk melingkar di meja makan. Ibu memang sudah lama tak menyukaiku, tapi hari itu Denis sanggup membujuknya untuk makan malam bersama, dengan satu tujuan.“Bu, aku dan Ayu sudah setahun lebih menjalin hubungan.” Denis tiba-tiba bersuara. Mata ibu membeliak gusar seakan bisa menebak ke mana arah pembicaraan ini. “Di usia kami, rasanya pacaran terlalu lama pun tidak ada gunanya. Aku ingin menikahi Ayu, Bu. Kuharap ibu merestuinya.”“Tidak,” jawab sang ibu cepat.“Bu,” Denis berusaha membujuk.“Ayu. Lebih baik kamu pulang sekarang. Anggap saja pembicaraan ini tidak ada.”Aku menatap kedua orang di depanku bergantian. Dadaku mendadak sesak. Sorot mata itu tajam menguliti hatiku. Napasnya memburu menahan geram. Sebenci itukah dia padaku? Salahku apa padanya?“Denis, kamu ganteng. Sukses. Pintar. Apa perlu ibu yang mencarikanmu istri?” tanyanya sambil tetap melihatku. Aku mendapati bayanganku sendiri pias di sepasang bola mata yang nyalang itu. “Ayu bukan perempuan yang tepat buat kamu.”“Kenapa saya tidak pantas untuk Denis, Bu? Apa karena saya pernah menikah dan punya anak?” entah dari mana kudapatkan keberanian itu. Denis meremas lembut tanganku, seakan memintaku tenang. Namun, ibu telanjur menyulut sesak yang kutimbun menjadi kobaran api yang tak terkendali.“Saya cinta Denis. Denis cinta saya dan dia juga mau menerima Nizam, anak saya. Apa yang salah dengan itu?”“Salah. Ibu nggak mau punya mantu janda.”“Apa hanya karena status janda itu ibu mengorbankan kebahagiaan Denis?”“Tahu apa kamu tentang bahagianya Denis? Ibu yang membesarkan dia. Kamu baru setahun kenal dia sudah berani menceramahi ibu? Seperti ini perempuan yang mau kamu nikahi, Den?”“Bu, tenang. Ingat, ibu ada sakit jantung.” Denis mengelus tangan ibunya, sementara tangan lainnya masih menggenggamku erat.“Pokoknya sampai mati, ibu nggak mau punya mantu Ayu.” Dalam sekejap, amarah itu merobek jantungnya. Ibu terkesiap memegangi dada. Di tengah usahanya menarik napas yang begitu menyakiti jantungnya, ia masih menatapku penuh benci.“Ayu,” suara ibu memanggilku kembali dari kenangan menyakitkan itu. Aku menoleh dan berusaha tersenyum. “Ibu bukannya benci sama kamu. Kamu anaknya baik. Cantik. Denis juga cerita bagaimana usaha kamu membagi waktu antara kerja dan anak. Kamu perempuan yang kuat. Tapi untuk menjadi istri Denis,…”Aku diam menanti kata-kata ibu selanjutnya. Jantungku berlompatan tak keruan, tapi berusaha tersenyum.“Ibu memohon dengan sangat,” ujarnya lirih. “Tinggalkan Denis. Tolak lamarannya. Ibu nggak akan bisa ikhlas kalau mantu ibu seorang janda beranak satu. Ibu rela melakukan apa saja. Kamu boleh minta apa saja, asal tinggalkan Denis. Jangan menikah dengan Denis.”“Kenapa, Bu?”“Apa salah kalau ibu ingin punya mantu wanita lajang? Apa salah kalau ibu tidak ingin Denis terjebak dalam tanggung jawab besar membesarkan anakmu? Denis belum siap untuk itu. Kamu tahu apa cibiran orang tentang janda? Menurutmu apa Denis layak diperlakukan seperti itu?”Hatiku teriris habis tak tersisa mendapati kata-kata itu. Sehina itukah aku di mata ibu? Aku tertunduk menyembunyikan mata yang berkaca-kaca.“Janji sama ibu, Ayu. Jangan nikahi Denis.” Ibu berujar lirih. Nadanya penuh iba dan ratap. Sebagai sesama ibu, aku berusaha mengerti keinginannya untuk membahagiakan putranya. Aku punya anak. Aku pun ingin anakku bahagia. Namun, bahagia atas nama siapa?Denis datang dengan dua botol air mineral di kedua tangan. Dua botol itu seperti aku dan ibu. Sama-sama membawa kebahagiaan untuk Denis, tapi hanya satu yang bisa dipilih. Aku atau ibu. Denis menatap kami cerah seakan tak sanggup menyembunyikan girang melihat kami bersanding dalam tenang. Namun, tahukah dia apa yang baru kami bahas?“Ayu, ibu mohon. Janji sama ibu.”“Iya,” jawabku lirih menyerah. “Saya janji. Saya tidak akan menikahi Denis.”***Aku melangkah gontai menuju ruang tengah. Ada Nizam tergolek nyenyak di sofa di depan televisi. Inah, pembantuku, buru-buru menghampiri seakan takut aku meledak marah. “Dek Nizam katanya mau nungguin ibu pulang,” ujarnya takut-takut. “Tadi sudah saya suruh tidur di kamar, tapi nggak mau.”“Nggak apa-apa,” jawabku lemah. Aku menghampiri tubuh mungil itu. Tangannya menggenggam selembar kertas yang hampir lunglai jatuh ke lantai. Perlahan kuambil kertas itu, berharap Nizam tidak terbangun. Hatiku mencelos kala kulihat yang tertera di sana.Sebuah lukisan krayon warna warni. Sebuah rumah dengan pagar kayu dan diapit pohon apel besar. Di depannya ada tiga orang. Masing-masing dinamai Nizam, Bunda, dan Ayah Denis. Aku langsung membekap mulut menahan suara terisak. Hatiku tercabik-cabik kecil. Perihnya menjalar sampai ke ujung kepala.“Bunda?” Nizam seperti menyadari kedatanganku. Buru-buru kuhapus air mata yang siap jatuh. Sepasang mata itu mengerjap tanpa dosa, lalu buru-buru ia memelukku. “Gambarnya jelek ya Bunda? Besok Nizam gambarin yang lebih bagus. Nanti Nizam gambarin dua. Satu ditaruh sini, satu lagi ditaruh rumah Om Denis ya? Terus kapan Nizam bisa panggil Om Denis papa?”Celotehan itu menderas, sederas pilu yang mencacah kepalaku. Aku hanya bisa memeluknya. Lagi-lagi aku mencari kekuatan pada tubuh mungil yang seharusnya kulindungi. Air mata jatuh satu-satu, terus menerus beriringan membasahi punggung Nizam.“Bunda, Nizam nggak sabar punya ayah seperti Om Denis.”Oh anakku,… maafkan bunda, sayang.***GM, 5 Juli 2012
Dimuat di Majalah Good Housekeeping edisi November 2014 Tanganku ragu membuka pintu berhiaskan poster Ben 10 itu dan hiasan gantung kayu bertulis Nizam’s Room. Kuusap wajahku beberapa kali sampai tak ada air mata tersisa lagi. Kupasang senyum terbaik yang kupunya. Kusuguhkan hanya wajah bahagia padanya.“Belum bobo, sayang?” sapaku.Nizam menatapku dari balik selimut. Binar sepasang mata, senyum yang merekah, dan uluran tangan memohon pelukan, semuanya kurekam erat-erat. Itulah pemandangan yang mengusir semua lelah dan menyirami hatiku dengan asa. Nizamlah yang membuat hidupku jauh lebih berharga sepeninggal mantan suamiku. “Bunda kok baru pulang jam segini?”“Maaf ya. Kamu nungguin Bunda?”Nizam mengangguk cepat beberapa kali. Pipi gembilnya naik turun mengikuti irama kepala. Langsung kupeluk dia dan kuserang dengan ciuman bertubi-tubi di seluruh wajahnya. Nizam terkekeh kegelian dan meronta-ronta. Kuhirup habis wangi tubuhnya seperti pecandu yang mengisap bakaran daun kanabis. “Bunda diantar sama Om Denis?” tanya Nizam polos. Sejenak aku menatapnya sembari menimbang apakah harus mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Jujur saja. Aku pun mengangguk cepat.“Kenapa Om Denis nggak mampir ke kamar Nizam dan bacakan dongeng?”“Om Denis harus buru-buru pulang. Sudah malam, kan?” aku melirik ke arah jam dinding. Jam sembilan lebih sedikit.“Bun, kapan Om Denis jadi papa Nizam?” ujarnya tiba-tiba. Pandangannya mengunci mataku. Sorot itu mampu membendung niatku untuk berbohong. Aku tak sanggup mendustai sepasang mata malaikat di depanku.“Teman-teman Nizam di sekolah bilang Bunda akan menikah sama Om Denis. Nizam akan punya papa baru. Kapan, Bun? Masih lama ya?”Sepasang mata itu langsung menyayat hatiku. Aku langsung memeluknya. Diam-diam air mataku merembes perlahan.“Nizam mau punya papa sebaik Om Denis, Bun. Cepat nikah ya, biar Om Denis bisa pindah kemari. Jadi Bunda sama Nizam nggak kesepian lagi.”Sekuat apa pun aku menahan suara, isakan itu sanggup menyelinap keluar dari bibirku. Air mataku semakin deras mengalir. Kupeluk Nizam makin erat. Bocah lima tahun itu sedikit meronta, tapi ia seakan paham, akhirnya memilih diam.“Bunda, kenapa nangis? Nizam nakal, ya?” tanyanya sambil mengelus punggungku.Tenggorokanku tercekat. Tak ada kata yang keluar. Seharusnya padakulah Nizam mencari ketenangan. Namun, aku seakan mencari kekuatan pada pelukan rapuh ini. Nizam terus mengelus punggungku. Kubiarkan malam yang makin tua di sana membawa bayang-bayang Denis menjauh. Biarkan aku berbagi hangat sejenak di ranjang Nizam.“Cup cup, Bunda, jangan nangis ya. Cup cup,” ujar Nizam polos.***Parsel buah di tanganku bergetar hebat. Tanpa banyak bicara, Denis mengambilnya dariku dengan satu tangan, lalu tangan lainnya menggenggam tanganku. Bisa kurasakan perbedaan kedua kulit kami. Tangannya besar dan hangat. Seperti selimut, tangan itu menangkup penuh pada tangan mungilku yang dingin. Ia pasti bisa menyadari badai yang bergemuruh di dadaku.“Operasi jantung ibu berhasil. Ibu akan baik-baik saja,” hiburnya. Siapa yang tengah dia hibur? Dirinya sendirikah lantaran sang ibu akhirnya lolos dari maut? Atau menghiburku yang sejak beberapa hari lalu tenggelam dari rasa bersalah?“Kamu yakin sakit jantung ibu nggak akan kambuh kalau melihatku?”“Tadinya kupikir begitu. Tapi ibu sendiri yang ingin ketemu kamu.”Aku menghela napas perlahan. Ini di luar dugaan. Ibu akhirnya mau menemuiku setelah drama panjang kami beberapa waktu lalu. Aku tak bisa menebak apa yang ada di kepala ibu.“Ibumu nggak pernah suka sama aku,” jawabku lirih.“Ibu cuma belum kenal sama kamu. Selama ini aku coba bujuk ibu. Mungkin setelah operasi itu, pikiran ibu jadi lebih terbuka. Siapa tahu ibu merestui kita?”“Ibu mana yang rela anak bujangnya menikah sama janda cerai beranak satu?” Denis tersentak menolehku. Ting!Denting lift terbuka dan percakapan kami berhenti sampai di sana. Sejenak aku ragu keluar dari sana untuk bertemu ibunya. Namun, tangannya menarik pelan. Seakan-akan hangatnya enggan melepasku pergi. Ibu duduk di kursi roda. Perawat tengah membawanya berjalan-jalan ke taman rumah sakit. Duduknya tenang dengan tiang infus menjulang di belakang. Wajahnya nampak segar. Mungkin darah sudah mengalir sempurna di tubuhnya berkat operasi itu. Namun tetap saja, tak ada senyum yang menyambutku. Hatiku langsung dicengkeram perasaan dingin. Kami semua sejenak memandangi pepohonan dan air mancur dalam diam. Kulirik ibu. Wajahnya tenang, sesekali terpejam. Tak ada tanda beliau akan menyerangku dengan kata-kata pedasnya seperti terakhir kami bertemu.“Den, tolong belikan ibu air putih. Kamu juga mau?” tawarnya padaku. Aku tersentak kaget dan menggeleng cepat. Denis sedikit ragu, tapi aku tersenyum. Kuyakinkan kalau kami berdua akan baik-baik saja di sini, walau sebenarnya diriku sendiri meragukannya.Aku melihat punggung Denis yang menjauh. Ada keheningan yang tumbuh di antara aku dan sang ibu. Aku memberanikan diri menatapnya. “Kamu masih ingat terakhir kita ketemu?” tanya ibu seakan tahu aku tengah mengamatinya. Aku mengangguk. “Denis bilang sama ibu kalau dia mau nikah sama kamu.”Kata-kata itu membawaku kembali pada pertemuan minggu lalu. Aku, Denis, dan sang ibu duduk melingkar di meja makan. Ibu memang sudah lama tak menyukaiku, tapi hari itu Denis sanggup membujuknya untuk makan malam bersama, dengan satu tujuan.“Bu, aku dan Ayu sudah setahun lebih menjalin hubungan.” Denis tiba-tiba bersuara. Mata ibu membeliak gusar seakan bisa menebak ke mana arah pembicaraan ini. “Di usia kami, rasanya pacaran terlalu lama pun tidak ada gunanya. Aku ingin menikahi Ayu, Bu. Kuharap ibu merestuinya.”“Tidak,” jawab sang ibu cepat.“Bu,” Denis berusaha membujuk.“Ayu. Lebih baik kamu pulang sekarang. Anggap saja pembicaraan ini tidak ada.”Aku menatap kedua orang di depanku bergantian. Dadaku mendadak sesak. Sorot mata itu tajam menguliti hatiku. Napasnya memburu menahan geram. Sebenci itukah dia padaku? Salahku apa padanya?“Denis, kamu ganteng. Sukses. Pintar. Apa perlu ibu yang mencarikanmu istri?” tanyanya sambil tetap melihatku. Aku mendapati bayanganku sendiri pias di sepasang bola mata yang nyalang itu. “Ayu bukan perempuan yang tepat buat kamu.”“Kenapa saya tidak pantas untuk Denis, Bu? Apa karena saya pernah menikah dan punya anak?” entah dari mana kudapatkan keberanian itu. Denis meremas lembut tanganku, seakan memintaku tenang. Namun, ibu telanjur menyulut sesak yang kutimbun menjadi kobaran api yang tak terkendali.“Saya cinta Denis. Denis cinta saya dan dia juga mau menerima Nizam, anak saya. Apa yang salah dengan itu?”“Salah. Ibu nggak mau punya mantu janda.”“Apa hanya karena status janda itu ibu mengorbankan kebahagiaan Denis?”“Tahu apa kamu tentang bahagianya Denis? Ibu yang membesarkan dia. Kamu baru setahun kenal dia sudah berani menceramahi ibu? Seperti ini perempuan yang mau kamu nikahi, Den?”“Bu, tenang. Ingat, ibu ada sakit jantung.” Denis mengelus tangan ibunya, sementara tangan lainnya masih menggenggamku erat.“Pokoknya sampai mati, ibu nggak mau punya mantu Ayu.” Dalam sekejap, amarah itu merobek jantungnya. Ibu terkesiap memegangi dada. Di tengah usahanya menarik napas yang begitu menyakiti jantungnya, ia masih menatapku penuh benci.“Ayu,” suara ibu memanggilku kembali dari kenangan menyakitkan itu. Aku menoleh dan berusaha tersenyum. “Ibu bukannya benci sama kamu. Kamu anaknya baik. Cantik. Denis juga cerita bagaimana usaha kamu membagi waktu antara kerja dan anak. Kamu perempuan yang kuat. Tapi untuk menjadi istri Denis,…”Aku diam menanti kata-kata ibu selanjutnya. Jantungku berlompatan tak keruan, tapi berusaha tersenyum.“Ibu memohon dengan sangat,” ujarnya lirih. “Tinggalkan Denis. Tolak lamarannya. Ibu nggak akan bisa ikhlas kalau mantu ibu seorang janda beranak satu. Ibu rela melakukan apa saja. Kamu boleh minta apa saja, asal tinggalkan Denis. Jangan menikah dengan Denis.”“Kenapa, Bu?”“Apa salah kalau ibu ingin punya mantu wanita lajang? Apa salah kalau ibu tidak ingin Denis terjebak dalam tanggung jawab besar membesarkan anakmu? Denis belum siap untuk itu. Kamu tahu apa cibiran orang tentang janda? Menurutmu apa Denis layak diperlakukan seperti itu?”Hatiku teriris habis tak tersisa mendapati kata-kata itu. Sehina itukah aku di mata ibu? Aku tertunduk menyembunyikan mata yang berkaca-kaca.“Janji sama ibu, Ayu. Jangan nikahi Denis.” Ibu berujar lirih. Nadanya penuh iba dan ratap. Sebagai sesama ibu, aku berusaha mengerti keinginannya untuk membahagiakan putranya. Aku punya anak. Aku pun ingin anakku bahagia. Namun, bahagia atas nama siapa?Denis datang dengan dua botol air mineral di kedua tangan. Dua botol itu seperti aku dan ibu. Sama-sama membawa kebahagiaan untuk Denis, tapi hanya satu yang bisa dipilih. Aku atau ibu. Denis menatap kami cerah seakan tak sanggup menyembunyikan girang melihat kami bersanding dalam tenang. Namun, tahukah dia apa yang baru kami bahas?“Ayu, ibu mohon. Janji sama ibu.”“Iya,” jawabku lirih menyerah. “Saya janji. Saya tidak akan menikahi Denis.”***Aku melangkah gontai menuju ruang tengah. Ada Nizam tergolek nyenyak di sofa di depan televisi. Inah, pembantuku, buru-buru menghampiri seakan takut aku meledak marah. “Dek Nizam katanya mau nungguin ibu pulang,” ujarnya takut-takut. “Tadi sudah saya suruh tidur di kamar, tapi nggak mau.”“Nggak apa-apa,” jawabku lemah. Aku menghampiri tubuh mungil itu. Tangannya menggenggam selembar kertas yang hampir lunglai jatuh ke lantai. Perlahan kuambil kertas itu, berharap Nizam tidak terbangun. Hatiku mencelos kala kulihat yang tertera di sana.Sebuah lukisan krayon warna warni. Sebuah rumah dengan pagar kayu dan diapit pohon apel besar. Di depannya ada tiga orang. Masing-masing dinamai Nizam, Bunda, dan Ayah Denis. Aku langsung membekap mulut menahan suara terisak. Hatiku tercabik-cabik kecil. Perihnya menjalar sampai ke ujung kepala.“Bunda?” Nizam seperti menyadari kedatanganku. Buru-buru kuhapus air mata yang siap jatuh. Sepasang mata itu mengerjap tanpa dosa, lalu buru-buru ia memelukku. “Gambarnya jelek ya Bunda? Besok Nizam gambarin yang lebih bagus. Nanti Nizam gambarin dua. Satu ditaruh sini, satu lagi ditaruh rumah Om Denis ya? Terus kapan Nizam bisa panggil Om Denis papa?”Celotehan itu menderas, sederas pilu yang mencacah kepalaku. Aku hanya bisa memeluknya. Lagi-lagi aku mencari kekuatan pada tubuh mungil yang seharusnya kulindungi. Air mata jatuh satu-satu, terus menerus beriringan membasahi punggung Nizam.“Bunda, Nizam nggak sabar punya ayah seperti Om Denis.”Oh anakku,… maafkan bunda, sayang.***GM, 5 Juli 2012
Published on March 27, 2015 08:15
[CERPEN] - Sepotong Rindu
Cerpen ini masuk ke dalam antologi "Yang Dibalut Lumut" sebagai karya 30 besar Lomba Kreativitas Pemuda 2003 kategori Cerpen yang diadakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aku menulisnya saat masih kelas 3 SMA. Berkat cerpen ini, aku diajak masuk ke dunia sastra dan bertemu para penggiatnya.
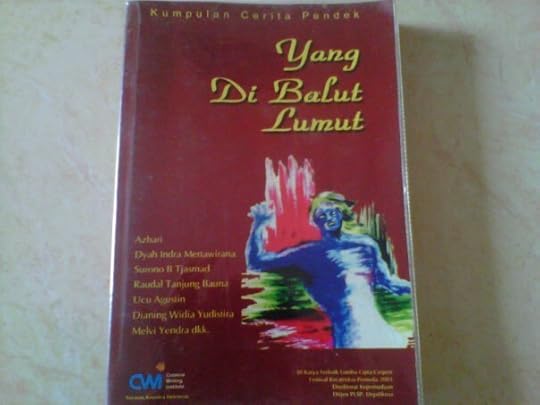
Malam selarut ini. Dingin diantarkan oleh hujan. Kehangatan pun dinanti. Teguh cuma duduk sambil termangu-mangu memandangi sisa pekerjaannya. Letihnya menggunung, sedari pagi berkutat dengan mesin dan oli. Ada sebongkah kerinduan memeluk batinnya. Detik-detik terus berlalu. Sepuluh menit lagi jam berdentang sebelas kali. Telepon berdering memecah keheningan yang diciptakan malam. Teguh setengah berlari meraihnya. Berdoa semoga yang dirindukannya merasakan kerinduan ini. “Halo?” Teguh menyapa penuh harap. “Teguh ya? Ini ibu, nak. Bagaimana kabarmu? Sehat? Sudah makan? Lalu anak-anakmu, bagaimana Gino, Iin, dan Lisa? Mereka baik-baik saja?” suara serak itu menyerocos. Teguh menghela napas. Harapannya pupus. “Kami baik-baik saja, bu, pokok’esehat semua. Ada apa ibu telepon malam-malam?” “Lho, ndak salah thoibu kangen sama anak sendiri. Kamu lagi ngapain?” “Saya sedang mengurus surat-surat order buat bengkel, bu. Anak-anak sudah tidur,” bohongnya. Ibu pasti senewen bila tahu anaknya duduk di ranjang sendiri di tengah hujan lebat sambil memeluk sepi. “Rumi? Piyé kabar istrimu?” tanya ibu agak menyelidik. “Baik-baik saja. Baru saja dia menelepon. Dia sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Saya bangga, bu, punya istri seperti Rumi. Cerdas, cita-citanya tinggi, dan energik,” “Walah, ibu malah nggak setuju kalau dia kuliah lagi. Terlalu tinggi. Toh dia wanita yang punya kodrat mengurus rumah tangga. Ibu pingin punya mantu yang sederhana, keibuan, pintar masak, dan tinggal di rumah. Rumi terlalu modern buat ibu,”Teguh kembali diam. Ia sangat malas meladeni ibunya berdebat. Sampai tiga belas tahun pernikahannya dengan Rumi, ibu tetap memendam kekecewaan. Ibu memang tidak terlalu suka Rumi. Untung saja, ibu terus berusaha menerimanya. Walau itu akan memakan waktu lama. “Kok rasanya hati ibu ini nggak enak. Seperti mau ada sesuatu. Benar kan semua baik-baik saja? Rumi masih sering telepon kamu, kan? Ibu kok jadi takut dia kecantol bule Singapura,” “Enggak ada apa-apa, bu. Ibu tenang saja. Kalau ada apa-apa, saya kabari.”“Yo wis, kamu istirahat. Ojo kecapekan,”“Inggih,”Teguh memandang foto Rumi yang bersanding dengan pesawat telepon yang gagangnya baru ia letakkan. Rumi memang muda dan cantik. Teguh mendadak merasa tua sekali karena usianya yang terpaut sebelas tahun. Rumi juga pandai. Sekarang ia mendapat tawaran studi S2 di Singapura oleh perusahaan tempat dia bekerja. Memang berat melepaskan istri secantik itu ke luar negeri sendirian. Tapi Teguh tahu, inilah cita-cita Rumi. Pendidikan dan jabatan yang cemerlang. Itulah yang membuat Teguh mengkeret. Bayangkan! Dia cuma lulusan STM. Walaupun dua bengkel di bawah kepemimpinannya, apakah cukup pantas bersanding dengan seorang manajer pemasaran perusahaan ekspor-impor? Teguh malas menjawabnya.Dia merasa tidak enak membohongi ibunya. Rumi sudah dua minggu tidak meneleponnya. Teguh juga tidak tahu nomor telepon Rumi di Singapura. Rumi menolak memberikannya. Biarlah saya yang menelepon mas, nanti tagihan telepon rumah membengkak, begitu pesannya. Teguh juga bingung kalau anak-anak mulai menanyakan Rumi. Dia tidak terbiasa berbohong. Tapi kini kebohongan mulai akrab dengan bibirnya. Telepon kembali berdering. Teguh masih mengharap Rumi yang meneleponnya.“Halo? Teguh ya? Ini Mami,”Rasanya mata Teguh menjadi berat. Kantuk mulai menyerbunya. Ia dua kali lebih malas menerima telepon dari mertuanya. Mami Rumi tidak kalah cerewetnya dengan ibu. Bila kedua besan itu bertemu, Teguh harus membiasakan telinganya dengan nada berisik. “Teguh, bagaimana kabar Rumi? Dia belum telepon mami,”“Rumi baik-baik saja, mi. Dia baru saja telepon saya. Katanya lagi sibuk dengan tugas kuliah. Makanya belum sempat telepon mami. Tapi tadi dia titip salam kangen buat mami,”“Oh ya? Itu baru anak mami,”Teguh merasa tengkuknya lelah.“Kamu sudah siapkan hadiah apa untuk kepulangan dia dua bulan nanti?”“Belum, mi.”“Masak Rumi nggak dikasih sesuatu atas kesuksesannya. Mestinya kamu bangga punya istri cerdas seperti Rumi. Dengan kemampuan seperti itu, Rumi bisa mendapatkan lelaki manapun yang dia mau. Kamu harus berusaha menjaga dia, menyenangkan hatinya, melindungi, dan menyayanginya. Jangan sampai dia tertarik pria lain,”Teguh menghela napas selirih mungkin. Mami memang sedikit tidak suka dengannya. Mungkin di mata mami, Teguh cuma montir yang kebetulan punya dua bengkel lalu berhasil menikahi bidadari berotak cemerlang. Mami juga sedikit cemberut melihat rumah pemberian Teguh yang tidak berlantai dua. Sering pula Teguh merasa mami sedikit meremehkan VW tahun 70annya. Mungkin menurut mami, Rumi lebih pantas menikah dengan orang yang punya rumah mewah lengkap dengan BMW.“Jangan bilang Rumi, ya. Mami sudah belikan kalian sepasang tiket ke Lombok plus akomodasi supaya kalian bisa berduaan. Bulan madu kedua, gitu.”Bulan madu? Tawaran ini lebih terdengar seperti pamer kekayaan di telinga Teguh.“Terima kasih, mi. Mami baik sekali,” pujinya datar.“Bukan apa-apa. Anggap saja hadiah,”Teguh meletakkan gagang telepon dengan malas setelah mami mengucapkan selamat malam. Detik ini dia merasa pernikahannya dengan Rumi terasa berat. Ibu sedikit tidak suka dengan “kecanggihan” Rumi, sedangkan mami agak kurang berkenan dengan Teguh yang “konservatif”. Mungkin pernikahan ini salah. Mungkin seharusnya ia menikah dengan Siti, anak pak RT kampung ibunya tinggal. Dan Rumi menikah dengan dokter gigi yang dulu sempat melamarnya. Hebatnya, Rumi selalu membuktikan kesetiaannya. Tak terhitung eksekutif muda sampai bos bangkotan yang mengejarnya. Namun, dengan bangga ia menunjukkan cincin kawin di jari manisnya. Teguh pun selalu diajak dalam tur kantor atau gala dinner menemani Rumi. Itu usaha Rumi membuat Teguh eksis. Yang terjadi, pria itu malah semakin terperosok dengan rasa mindernya. Bagaimana bila di sana-di negara yang penuh impian itu-Rumi bertemu dengan pria yang lebih baik? Makmur dalam segala aspek kehidupan. Mungkinkah Rumi berpaling dari cintanya? Bagaimana jika terjadi sedikit perselingkuhan? Apa yang harus dilakukan? Dalam sedetik, Teguh merasa bukan apa-apa.Malam terus beranjak. Pria itu merasa semakin sumpek. Ia membuka agendanya. Ia ingin menuangkan kegundahannya. Berpuisi atau berprosa. Mungkin terdengar agak cengeng, tapi Teguh tidak tahu harus berujar pada siapa.Aku ingin Rumi bahagia. Aku cuma berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Istriku wanita paling hebat. Keluarga kami sempurna dan bahagia. Aku justru takut kesempurnaan ini malah mengantarkan pada sesuatu yang cacat.Rasa kantuk mulai menyeret Teguh untuk bermimpi. Dan kini ia menemukan Rumi dalam tidurnya.***Ciuman kecil di pipi itu membuat Teguh tersenyum lega. Dua bulan tepat sejak malam itu, Rumi kini berdiri di hadapannya. Wajahnya lebih segar dan berseri. Rambutnya dipotong pendek dan tubuhnya sedikit berisi. Nampaknya hidup Rumi tidak terlantar di sana. Teguh jadi malu melihat tubuhnya sendiri. Bobotnya susut delapan kilo sejak kepergian Rumi.“Mas Teguh agak kurus. Pasti susah makan, ya? Atau kangen ya sama Rumi?”Teguh tersipu sendiri.“Bunda! Bunda pulang! Bawa oleh-oleh apa?” ketiga anak itu mengerumuni Rumi seperti serombongan lebah yang menemukan sebotol madu.Rumi membongkar bawaannya. Banyak oleh-oleh yang ia beli. Entah berapa dollar Singapura yang dihabiskan Rumi untuk barang sebanyak itu. Rumi menyodorkan seperangkat perkakas mobil yang disimpan dalam kotak aluminium metalik sebesar boks sepatu untuk suaminya. Gino girang bukan main saat bundanya membawakan discman keluaran terbaru. Untuk Iin dan Lisa, Rumi menghadiahkan sebuah gaun cantik warna hijau yang modelnya berbeda. Tidak lupa dia membawa tasbih wangi untuk bik Iyem, sehelai kain sutra untuk ibu, dan parfum elit buat mami. “Pasti habis uang banyak ya Rum?”Rumi menggeleng. “Oleh-oleh nggak boleh dilihat harganya, mas. Pamali,”Teguh berusaha tersenyum. Kepalanya mulai berdenyut-denyut membayangkan berapa uang yang dihabiskan istrinya. Mungkin itu tidak seberapa untuk penghasilan seorang manajer, tapi buat Teguh? Ia bergidik pelan.Rumi membereskan baju-bajunya di lemari. Baju kotor sudah ditumpuk di mesin cuci. Perasaannya sedikit lega. Belakangan ini ada kegalauan yang sempat singgah. Ia takut juga kalau Mas Teguh berpaling hati pada yang lain. Setahun studi di luar negeri bukan waktu yang sebentar. Apa saja bisa terjadi. Siapa tahu Mas Teguh kesepian dan ingin mencari hiburan. Perselingkuhan? Rumi terbiasa dengan itu. Lingkungan kerjanya membuat fenomena ini tumbuh dengan subur. Untung saja, Mas Teguh tetap seperti dulu. Tidak berubah. Memang seharusnya dia tidak meragukan kesetiaan Mas Teguh.Saat meletakkan sweter birunya di bagian lemari paling atas, ada yang jatuh. Sebuah agenda yang diselipkan di sudut atas dekat tumpukan handuk. Rumi tergoda untuk membukanya. Suaminya sedang sibuk dengan anak-anak. Tidak ada salahnya membuka agenda Mas Teguh. Toh mereka suami istri. Tidak sepantasnya ada rahasia di antara mereka berdua.Rumi tersenyum sendiri. Rupanya di agenda itu tertoreh puisi-puisi singkat sebagai wujud kerinduan Mas Teguh padanya selama Rumi pergi studi. Rupanya suaminya memiliki sisi romantis. Ingin menangis rasanya.Matanya pun tertuju pada tulisan Mas Teguh yang dibuat tepat dua bulan lalu. Sebuah tulisan yang menohok hatinya.Aku ingin Rumi bahagia. Aku cuma berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Istriku wanita paling hebat. Keluarga kami sempurna dan bahagia. Aku justru takut kesempurnaan ini malah mengantarkan pada sesuatu yang cacat.Rumi merasakan matanya basah. Hatinya seakan terimpit. Tulisan ini begitu mengena di batinnya. Ia bertanya-tanya, sedang apakah aku saat Mas Teguh menulis ini?Deeggg,… Rumi baru ingat. Malam itu dia sedang di Singapura. Dia sedang di sebuah apartemen, di sebuah penthouse kelas elit. Betapa sulitnya menampik undangan dari seorang konglomerat Perancis. Tampan, tegap, muda, modis, energik, dan memiliki sebuah limo pribadi. Belum lagi mata dan sikap yang romantis, pria itu menarik perhatiannya.Rumi baru ingat. Saat itu nama Mas Teguh tidak ada dalam ingatannya. Pesona pria itu menghapus bayang-bayang suaminya dalam hitungan detik. Belum lagi saat pria itu menggandengnya, membelainya,… Malam itu ia menikmati ciuman dan pelukan pria itu. Siapa namanya ya? Oh ya, namanya Louis. Rumi pun dibawa Mr. Louis ke dalam kenikmatan baru yang belum pernah ia rasakan dengan Mas Teguh. Variasi intim yang mungkin tidak terlintas di benak Mas Teguh. Apalagi saat itu ia benar-benar membutuhkan kasih sayang. Mas Teguh ada di lintas negara yang berbeda. Bisikan setan yang selama ini dihindarinya, akhirnya hinggap dan meresap.Air matanya meleleh. Berdosakah dia melewatkan malam itu dengan Mr. Louis? Bukankah istri yang baik tidak akan mengkhianati suaminya? Rumi malah berbagi ranjang dengan pria yang baru dia kenal melalui makan malam bisnis. Bagaimana kalau suaminya tahu? Dari kamar, ia mendengar suara tawa Mas Teguh bercanda dengan ketiga anaknya. Rumi ketakutan. Badannya menggigil. Ia mendengar suara napas yang terhembus lemah dalam rongga tubuhnya,… bergerak pelan di dalam rahimnya.***Tangerang, 13 Juni 2003
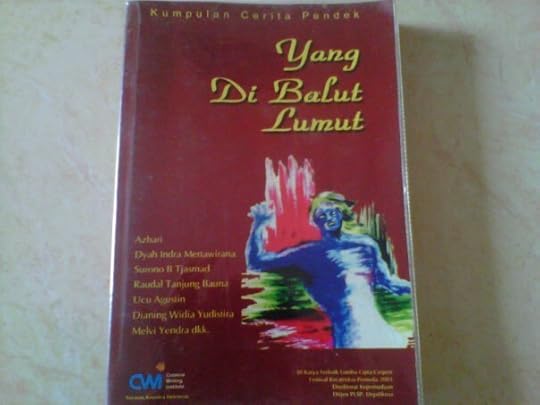
Malam selarut ini. Dingin diantarkan oleh hujan. Kehangatan pun dinanti. Teguh cuma duduk sambil termangu-mangu memandangi sisa pekerjaannya. Letihnya menggunung, sedari pagi berkutat dengan mesin dan oli. Ada sebongkah kerinduan memeluk batinnya. Detik-detik terus berlalu. Sepuluh menit lagi jam berdentang sebelas kali. Telepon berdering memecah keheningan yang diciptakan malam. Teguh setengah berlari meraihnya. Berdoa semoga yang dirindukannya merasakan kerinduan ini. “Halo?” Teguh menyapa penuh harap. “Teguh ya? Ini ibu, nak. Bagaimana kabarmu? Sehat? Sudah makan? Lalu anak-anakmu, bagaimana Gino, Iin, dan Lisa? Mereka baik-baik saja?” suara serak itu menyerocos. Teguh menghela napas. Harapannya pupus. “Kami baik-baik saja, bu, pokok’esehat semua. Ada apa ibu telepon malam-malam?” “Lho, ndak salah thoibu kangen sama anak sendiri. Kamu lagi ngapain?” “Saya sedang mengurus surat-surat order buat bengkel, bu. Anak-anak sudah tidur,” bohongnya. Ibu pasti senewen bila tahu anaknya duduk di ranjang sendiri di tengah hujan lebat sambil memeluk sepi. “Rumi? Piyé kabar istrimu?” tanya ibu agak menyelidik. “Baik-baik saja. Baru saja dia menelepon. Dia sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Saya bangga, bu, punya istri seperti Rumi. Cerdas, cita-citanya tinggi, dan energik,” “Walah, ibu malah nggak setuju kalau dia kuliah lagi. Terlalu tinggi. Toh dia wanita yang punya kodrat mengurus rumah tangga. Ibu pingin punya mantu yang sederhana, keibuan, pintar masak, dan tinggal di rumah. Rumi terlalu modern buat ibu,”Teguh kembali diam. Ia sangat malas meladeni ibunya berdebat. Sampai tiga belas tahun pernikahannya dengan Rumi, ibu tetap memendam kekecewaan. Ibu memang tidak terlalu suka Rumi. Untung saja, ibu terus berusaha menerimanya. Walau itu akan memakan waktu lama. “Kok rasanya hati ibu ini nggak enak. Seperti mau ada sesuatu. Benar kan semua baik-baik saja? Rumi masih sering telepon kamu, kan? Ibu kok jadi takut dia kecantol bule Singapura,” “Enggak ada apa-apa, bu. Ibu tenang saja. Kalau ada apa-apa, saya kabari.”“Yo wis, kamu istirahat. Ojo kecapekan,”“Inggih,”Teguh memandang foto Rumi yang bersanding dengan pesawat telepon yang gagangnya baru ia letakkan. Rumi memang muda dan cantik. Teguh mendadak merasa tua sekali karena usianya yang terpaut sebelas tahun. Rumi juga pandai. Sekarang ia mendapat tawaran studi S2 di Singapura oleh perusahaan tempat dia bekerja. Memang berat melepaskan istri secantik itu ke luar negeri sendirian. Tapi Teguh tahu, inilah cita-cita Rumi. Pendidikan dan jabatan yang cemerlang. Itulah yang membuat Teguh mengkeret. Bayangkan! Dia cuma lulusan STM. Walaupun dua bengkel di bawah kepemimpinannya, apakah cukup pantas bersanding dengan seorang manajer pemasaran perusahaan ekspor-impor? Teguh malas menjawabnya.Dia merasa tidak enak membohongi ibunya. Rumi sudah dua minggu tidak meneleponnya. Teguh juga tidak tahu nomor telepon Rumi di Singapura. Rumi menolak memberikannya. Biarlah saya yang menelepon mas, nanti tagihan telepon rumah membengkak, begitu pesannya. Teguh juga bingung kalau anak-anak mulai menanyakan Rumi. Dia tidak terbiasa berbohong. Tapi kini kebohongan mulai akrab dengan bibirnya. Telepon kembali berdering. Teguh masih mengharap Rumi yang meneleponnya.“Halo? Teguh ya? Ini Mami,”Rasanya mata Teguh menjadi berat. Kantuk mulai menyerbunya. Ia dua kali lebih malas menerima telepon dari mertuanya. Mami Rumi tidak kalah cerewetnya dengan ibu. Bila kedua besan itu bertemu, Teguh harus membiasakan telinganya dengan nada berisik. “Teguh, bagaimana kabar Rumi? Dia belum telepon mami,”“Rumi baik-baik saja, mi. Dia baru saja telepon saya. Katanya lagi sibuk dengan tugas kuliah. Makanya belum sempat telepon mami. Tapi tadi dia titip salam kangen buat mami,”“Oh ya? Itu baru anak mami,”Teguh merasa tengkuknya lelah.“Kamu sudah siapkan hadiah apa untuk kepulangan dia dua bulan nanti?”“Belum, mi.”“Masak Rumi nggak dikasih sesuatu atas kesuksesannya. Mestinya kamu bangga punya istri cerdas seperti Rumi. Dengan kemampuan seperti itu, Rumi bisa mendapatkan lelaki manapun yang dia mau. Kamu harus berusaha menjaga dia, menyenangkan hatinya, melindungi, dan menyayanginya. Jangan sampai dia tertarik pria lain,”Teguh menghela napas selirih mungkin. Mami memang sedikit tidak suka dengannya. Mungkin di mata mami, Teguh cuma montir yang kebetulan punya dua bengkel lalu berhasil menikahi bidadari berotak cemerlang. Mami juga sedikit cemberut melihat rumah pemberian Teguh yang tidak berlantai dua. Sering pula Teguh merasa mami sedikit meremehkan VW tahun 70annya. Mungkin menurut mami, Rumi lebih pantas menikah dengan orang yang punya rumah mewah lengkap dengan BMW.“Jangan bilang Rumi, ya. Mami sudah belikan kalian sepasang tiket ke Lombok plus akomodasi supaya kalian bisa berduaan. Bulan madu kedua, gitu.”Bulan madu? Tawaran ini lebih terdengar seperti pamer kekayaan di telinga Teguh.“Terima kasih, mi. Mami baik sekali,” pujinya datar.“Bukan apa-apa. Anggap saja hadiah,”Teguh meletakkan gagang telepon dengan malas setelah mami mengucapkan selamat malam. Detik ini dia merasa pernikahannya dengan Rumi terasa berat. Ibu sedikit tidak suka dengan “kecanggihan” Rumi, sedangkan mami agak kurang berkenan dengan Teguh yang “konservatif”. Mungkin pernikahan ini salah. Mungkin seharusnya ia menikah dengan Siti, anak pak RT kampung ibunya tinggal. Dan Rumi menikah dengan dokter gigi yang dulu sempat melamarnya. Hebatnya, Rumi selalu membuktikan kesetiaannya. Tak terhitung eksekutif muda sampai bos bangkotan yang mengejarnya. Namun, dengan bangga ia menunjukkan cincin kawin di jari manisnya. Teguh pun selalu diajak dalam tur kantor atau gala dinner menemani Rumi. Itu usaha Rumi membuat Teguh eksis. Yang terjadi, pria itu malah semakin terperosok dengan rasa mindernya. Bagaimana bila di sana-di negara yang penuh impian itu-Rumi bertemu dengan pria yang lebih baik? Makmur dalam segala aspek kehidupan. Mungkinkah Rumi berpaling dari cintanya? Bagaimana jika terjadi sedikit perselingkuhan? Apa yang harus dilakukan? Dalam sedetik, Teguh merasa bukan apa-apa.Malam terus beranjak. Pria itu merasa semakin sumpek. Ia membuka agendanya. Ia ingin menuangkan kegundahannya. Berpuisi atau berprosa. Mungkin terdengar agak cengeng, tapi Teguh tidak tahu harus berujar pada siapa.Aku ingin Rumi bahagia. Aku cuma berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Istriku wanita paling hebat. Keluarga kami sempurna dan bahagia. Aku justru takut kesempurnaan ini malah mengantarkan pada sesuatu yang cacat.Rasa kantuk mulai menyeret Teguh untuk bermimpi. Dan kini ia menemukan Rumi dalam tidurnya.***Ciuman kecil di pipi itu membuat Teguh tersenyum lega. Dua bulan tepat sejak malam itu, Rumi kini berdiri di hadapannya. Wajahnya lebih segar dan berseri. Rambutnya dipotong pendek dan tubuhnya sedikit berisi. Nampaknya hidup Rumi tidak terlantar di sana. Teguh jadi malu melihat tubuhnya sendiri. Bobotnya susut delapan kilo sejak kepergian Rumi.“Mas Teguh agak kurus. Pasti susah makan, ya? Atau kangen ya sama Rumi?”Teguh tersipu sendiri.“Bunda! Bunda pulang! Bawa oleh-oleh apa?” ketiga anak itu mengerumuni Rumi seperti serombongan lebah yang menemukan sebotol madu.Rumi membongkar bawaannya. Banyak oleh-oleh yang ia beli. Entah berapa dollar Singapura yang dihabiskan Rumi untuk barang sebanyak itu. Rumi menyodorkan seperangkat perkakas mobil yang disimpan dalam kotak aluminium metalik sebesar boks sepatu untuk suaminya. Gino girang bukan main saat bundanya membawakan discman keluaran terbaru. Untuk Iin dan Lisa, Rumi menghadiahkan sebuah gaun cantik warna hijau yang modelnya berbeda. Tidak lupa dia membawa tasbih wangi untuk bik Iyem, sehelai kain sutra untuk ibu, dan parfum elit buat mami. “Pasti habis uang banyak ya Rum?”Rumi menggeleng. “Oleh-oleh nggak boleh dilihat harganya, mas. Pamali,”Teguh berusaha tersenyum. Kepalanya mulai berdenyut-denyut membayangkan berapa uang yang dihabiskan istrinya. Mungkin itu tidak seberapa untuk penghasilan seorang manajer, tapi buat Teguh? Ia bergidik pelan.Rumi membereskan baju-bajunya di lemari. Baju kotor sudah ditumpuk di mesin cuci. Perasaannya sedikit lega. Belakangan ini ada kegalauan yang sempat singgah. Ia takut juga kalau Mas Teguh berpaling hati pada yang lain. Setahun studi di luar negeri bukan waktu yang sebentar. Apa saja bisa terjadi. Siapa tahu Mas Teguh kesepian dan ingin mencari hiburan. Perselingkuhan? Rumi terbiasa dengan itu. Lingkungan kerjanya membuat fenomena ini tumbuh dengan subur. Untung saja, Mas Teguh tetap seperti dulu. Tidak berubah. Memang seharusnya dia tidak meragukan kesetiaan Mas Teguh.Saat meletakkan sweter birunya di bagian lemari paling atas, ada yang jatuh. Sebuah agenda yang diselipkan di sudut atas dekat tumpukan handuk. Rumi tergoda untuk membukanya. Suaminya sedang sibuk dengan anak-anak. Tidak ada salahnya membuka agenda Mas Teguh. Toh mereka suami istri. Tidak sepantasnya ada rahasia di antara mereka berdua.Rumi tersenyum sendiri. Rupanya di agenda itu tertoreh puisi-puisi singkat sebagai wujud kerinduan Mas Teguh padanya selama Rumi pergi studi. Rupanya suaminya memiliki sisi romantis. Ingin menangis rasanya.Matanya pun tertuju pada tulisan Mas Teguh yang dibuat tepat dua bulan lalu. Sebuah tulisan yang menohok hatinya.Aku ingin Rumi bahagia. Aku cuma berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Istriku wanita paling hebat. Keluarga kami sempurna dan bahagia. Aku justru takut kesempurnaan ini malah mengantarkan pada sesuatu yang cacat.Rumi merasakan matanya basah. Hatinya seakan terimpit. Tulisan ini begitu mengena di batinnya. Ia bertanya-tanya, sedang apakah aku saat Mas Teguh menulis ini?Deeggg,… Rumi baru ingat. Malam itu dia sedang di Singapura. Dia sedang di sebuah apartemen, di sebuah penthouse kelas elit. Betapa sulitnya menampik undangan dari seorang konglomerat Perancis. Tampan, tegap, muda, modis, energik, dan memiliki sebuah limo pribadi. Belum lagi mata dan sikap yang romantis, pria itu menarik perhatiannya.Rumi baru ingat. Saat itu nama Mas Teguh tidak ada dalam ingatannya. Pesona pria itu menghapus bayang-bayang suaminya dalam hitungan detik. Belum lagi saat pria itu menggandengnya, membelainya,… Malam itu ia menikmati ciuman dan pelukan pria itu. Siapa namanya ya? Oh ya, namanya Louis. Rumi pun dibawa Mr. Louis ke dalam kenikmatan baru yang belum pernah ia rasakan dengan Mas Teguh. Variasi intim yang mungkin tidak terlintas di benak Mas Teguh. Apalagi saat itu ia benar-benar membutuhkan kasih sayang. Mas Teguh ada di lintas negara yang berbeda. Bisikan setan yang selama ini dihindarinya, akhirnya hinggap dan meresap.Air matanya meleleh. Berdosakah dia melewatkan malam itu dengan Mr. Louis? Bukankah istri yang baik tidak akan mengkhianati suaminya? Rumi malah berbagi ranjang dengan pria yang baru dia kenal melalui makan malam bisnis. Bagaimana kalau suaminya tahu? Dari kamar, ia mendengar suara tawa Mas Teguh bercanda dengan ketiga anaknya. Rumi ketakutan. Badannya menggigil. Ia mendengar suara napas yang terhembus lemah dalam rongga tubuhnya,… bergerak pelan di dalam rahimnya.***Tangerang, 13 Juni 2003
Published on March 27, 2015 07:54
March 19, 2015
Love and The City ~ Pilih Karir atau Asmara?
Dalam Cinta, Tak Ada Pilihan Sederhana
Pernah nggak sih, kamu bingung memilih antara cinta dan karir. Masalah ini memang dialami banyak kaum perempuan ibukota, yang sering mengalami dilema dalam urusan karir dan asmara. Maklum, perempuan dituntut menjadi istri dan ibu yang baik, sekaligus dalam beberapa kondisi berkarir cemerlang.

Itulah ide awal Mas Andi dari komunitas @NBC_IPB dan mas Ijul, penggiat komunitas baca fiksi metropop. Mereka adalah bidan lahirnya buku ini. Setelah membuka kompetisi menulis dan menjaring naskah-naskah jempolan, aku (bersama beberapa penulis lainnya pula) diajak bergabung untuk memeriahkan proyek menulis ini. Lahirlah "Love and the City", yang merupakan omnibus cerpenku yang ke sebelas, sepanjang karirku menulis prosa.
Di "Love and The City" ini, aku menulis satu cerpen berjudul "Langkahan". Di cerpen ini, aku menggunakan tiga sudut pandang tokoh, di mana mereka melihat problematika karir dan asmara dari perspektif yang berbeda. Ada kultur Jawa, terlebih budaya Langkahan, yang sengaja kusisipkan sebagai nuansa penguat benang merah cerita.
Seperti apa sih, boleh ngintip nggak? Nih...
Kalau ada yang bertanya harta saya yang paling berharga, tentulah kedua anak perempuan saya. Diajeng Maheswari dan Anjani Kusumaputeri. Ajeng dan Jani, begitu saya memanggilnya. Kalau melihat pemandangan ini, sepertinya saya takkan percaya, kemarin keduanya bertengkar hidup tentang pilihan masing-masing.
Lusa Jani akan menikah dengan lelaki pilihannya. Dia bilang menikah adalah caranya membahagiakan diri sendiri. Walaupun tidak mudah bagi Ajeng, dia tetap merestui adiknya menikah duluan. Dan pagi ini, saya sengaja mengadakan upacara langkahan manten Jawa, di mana secara ritual adat, Jani memohon restu kakaknya. Agar pernikahannya lancar dan keduanya sama-sama bahagia.
Makin penasaran dengan ceritanya? Yuk, mampir dulu ke ulasannya di Goodreads dan di sini.
Dan daripada makin nggak keruan penasarannya, mari beli buku ini di toko buku kesayanganmu atau beli langsung di www.bukubukularis.com karena ada promo menarik di sana.
Pernah nggak sih, kamu bingung memilih antara cinta dan karir. Masalah ini memang dialami banyak kaum perempuan ibukota, yang sering mengalami dilema dalam urusan karir dan asmara. Maklum, perempuan dituntut menjadi istri dan ibu yang baik, sekaligus dalam beberapa kondisi berkarir cemerlang.

Itulah ide awal Mas Andi dari komunitas @NBC_IPB dan mas Ijul, penggiat komunitas baca fiksi metropop. Mereka adalah bidan lahirnya buku ini. Setelah membuka kompetisi menulis dan menjaring naskah-naskah jempolan, aku (bersama beberapa penulis lainnya pula) diajak bergabung untuk memeriahkan proyek menulis ini. Lahirlah "Love and the City", yang merupakan omnibus cerpenku yang ke sebelas, sepanjang karirku menulis prosa.
Di "Love and The City" ini, aku menulis satu cerpen berjudul "Langkahan". Di cerpen ini, aku menggunakan tiga sudut pandang tokoh, di mana mereka melihat problematika karir dan asmara dari perspektif yang berbeda. Ada kultur Jawa, terlebih budaya Langkahan, yang sengaja kusisipkan sebagai nuansa penguat benang merah cerita.
Seperti apa sih, boleh ngintip nggak? Nih...
Kalau ada yang bertanya harta saya yang paling berharga, tentulah kedua anak perempuan saya. Diajeng Maheswari dan Anjani Kusumaputeri. Ajeng dan Jani, begitu saya memanggilnya. Kalau melihat pemandangan ini, sepertinya saya takkan percaya, kemarin keduanya bertengkar hidup tentang pilihan masing-masing.
Lusa Jani akan menikah dengan lelaki pilihannya. Dia bilang menikah adalah caranya membahagiakan diri sendiri. Walaupun tidak mudah bagi Ajeng, dia tetap merestui adiknya menikah duluan. Dan pagi ini, saya sengaja mengadakan upacara langkahan manten Jawa, di mana secara ritual adat, Jani memohon restu kakaknya. Agar pernikahannya lancar dan keduanya sama-sama bahagia.
Makin penasaran dengan ceritanya? Yuk, mampir dulu ke ulasannya di Goodreads dan di sini.
Dan daripada makin nggak keruan penasarannya, mari beli buku ini di toko buku kesayanganmu atau beli langsung di www.bukubukularis.com karena ada promo menarik di sana.
Published on March 19, 2015 19:11
#LoveAtSchool, Ada Cinta di Sekolah!
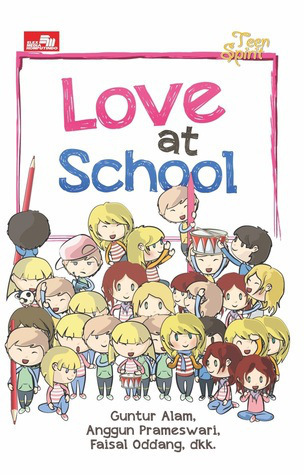
"Ia selalu ada.. Rasakan kehadirannya.."
Pernahkah kamu bertanya, mengapa senyuman yang selalu dia perlihatkan ketika melintasi kelasmu setiap pagi membuat jantungmu memompa darah lebih cepat?
Pernahkah kamu bertanya, mengapa obrolan tak serius di perpustakaan dengan dia menjadi pemicu mimpi indahmu di malam hari?
Atau, mengapa cemburu yang muncul setelah melihat dia berjalan ke kantin dengan yang lain membuat harimu terasa berantakan di sekolah?
Jangan menduga-duga jawaban. Mungkin itu cinta.
Sama seperti enam belas kisah yang ditulis oleh Guntur Alam, Anggun Prameswari, Faisal Oddang, Pretty Angelia, Ria Destriana, Fakhrisina Amalia Rovieq, Afgian Muntaha, Pipit Indah Mentari, Mel Puspita, Fitriyah, Karina Indah Pertiwi, Afin Yulia. Ruth Ismayati Munthe, juga Dilbar Dilara.
Mereka merasakan kehadirannya. Tak pernah absen.
Cinta itu selalu ada... di sekolah.
Ini adalah antologi bersama pertamaku di tahun 2015, sekaligus merupakan omnibus ke sepuluhku selama berkarir sebagai penulis prosa. Awalnya, ini merupakan proyek besutan sahabatku, Guntur Alam, yang memang berdedikasi tinggi memajukan dunia penulisan Indonesia melalui tangan-tangan penulis baru.
Napas utama serta benang merah buku ini adalah cinta di sekolah, persis dengan judulnya "Love at School". Tentu sudah bisa ditebak bahwa banyak cerita merah jambu dengan latar sekolah terangkum di buku ini.
Cerpen yang kutulis di buku ini berjudul "Dongeng Bunga Matahari". Ide awalnya adalah seorang murid yang naksir gurunya sendiri, terinspirasi dari beberapa pengalamanku sebagai guru. Untuk mengaitkannya dengan gaya roman depresi yang sering kupakai dalam tulisan, aku membubuhkan puisi dan ending yang membilurkan hati. Seperti apa ceritanya? Nih, kuberi sedikit cuplikannya...
Dulu bunga matahari adalah penjelmaan seorang dewi di khayangan. Dewi yang sangat cantik, berkulit kuning langsat dan berambut emas. Tapi dewi ini jatuh cinta pada mentari yang menyinari bumi. Sang dewi ingin sekali memiliki mentari yang memiliki senyum yang bisa menghangatkan dunia, tapi itu menyalahi aturan semesta. Ia pun dikutuk menjadi bunga. Ia memohon, walaupun telah dikutuk menjadi bunga, ia masih tetap bisa menatap senyum mentari yang ia cintai, dan jadilah ia bunga matahari yang mengikuti ke mana sang mentari pergi.
Kisah cinta yang menyedihkan, bukan? Karena itulah, aku sungguh suka bunga matahari. Karena seperti itulah kisah cintaku. Seperti dewi khayangan yang jatuh cinta pada sang mentari, aku jatuh cinta pada yang tak boleh dicintai. Pasti sebentar lagi aku akan dikutuk.
Penasaran dengan ceritanya? Yuk intip juga ulasannya di Goodreads dan di sini. Buruan beli bukunya dan kenanglah masa sekolahmu dengan cara yang manis, ... karena selalu ada cinta di sekolah!
Published on March 19, 2015 18:45
February 18, 2015
Berjanji Seribu Tahun
Flash Fiction ini ditulis untuk mengikuti program #FF2in1 dari Tiket.com dan nulisbuku.com #TiketBaliGratis.
oleh: Anggun Prameswari
Tak ada yang tahu bahwa di Kota Janji, menjulang sebuah patung perempuan. Jika kau pendatang seperti diriku, maka tentu kau takkan tahu apa sejarah patung itu. Namun, kalau kakek buyut dari kakekmu sempat menurunkan cerita, turun-temurun tak kurang suatu apapun, maka kau akan tahu bahwa patung itu jelmaan seorang perempuan yang menunggu kekasihnya.“Berapa lama?”“Jari siapa yang bisa menghitung?”“Cari saja angka yang mudah.”“Seribu tahun.”“Kenapa seribu? Buka sejuta?”“Kenapa pula bukan seratus?”“Ah siapa yang peduli? Intinya, ada perempuan yang jadi batu, dikutuk perasaan merananya sendiri .”“Apa kutukan itu bisa dihilangkan?”“Tentu. Tidak ada kutukan yang abadi.”“Caranya?”Orang-orang yang bergumam itu saling berpandangan. Mereka saling melemparkan sorot mata, sebagian tak tahu, sisanya entah bermakna apa.Aku yang mematung, menyapukan tangan ke permukaan batu itu. Tingginya hanya beda dua senti, dengan lumut nyaris melumuri setiap jengkal permukaannya. Tiap kusentuh, makin lekat di telapakku, makin erat pula perasaan aneh yang menyelimutiku.Ada lubang besar yang menganga, yang tak tersentuh kedalamannya, mendadak muncul di hatiku. Begitu tanganku tak lagi menyentuh permukaan batu itu, perasaan itu cepat menguap. Namun, sekejap kembali begitu aku menyentuhnya.Maka, aku menekankan telapak tanganku, membiarkan dinginnya memboboti kulit, menarikku lebih dalam. Kesedihan begitu mudah menarik hati siapapun yang tengah berduka.Sejak itu, setiap hari aku datang ke batu itu. Awalnya hanya untuk makan siang. Lama kelamaan, aku makan tiga kali—sarapan, makan siang, dan makan malam—di samping batu itu. Aku sering menawarinya macam-macam. Kadang bubur ayam, kue lapis, roti isi, atau susu coklat. Kuharap makanan bisa membantunya kembali bahagia. Siapa tahu, setelah bahagia, batu itu kembali menjelma menjadi perempuan yang dulu pernah menunggu kekasihnya di Kota Janji. Sayangnya, batu itu bergeming, tetap membatu.“Kau lihat perempuan itu?”“Iya, aneh. Setiap hari mengunjungi batu.”“Penyembah berhala?”“Ah, dia sekedar perempuan patah hati lainnya, senasib dengan legenda si batu.”Aku diam saja, berusaha abai. Tak ada yang memahamiku. Memahami betapa besarnya perasaan cinta yang harus kupendam selama seribu tahun. Hanya batu berlekuk tubuh perempuan inilah yang mengerti. Maka, kami makin akrab. Makin tak terpisahkan. Aku tidur di sana. Membaca, mengudap, melamun, bahkan memeluknya minimal tiga kali sehari. Berbagi kesedihan tidaklah dosa, bukan?Sampai akhirnya dia menemuiku. Kekasih yang selama ini kutunggu. Yang matanya bulat purnama dengan kulit cokelat madu. Dia menjemputku, di Kota Janji yang berprasasti batu perempuan merana.Tanpa sadar pipiku basah. Haru mengembangkan dadaku dengan harapan-harapan.“Pa,” tanya gadis cilik itu lagi. “Batunya aneh. Bentuknya mirip manusia.”“Iya, batunya ada sepasang. Dua-duanya perempuan.”“Pa, lihat, yang di sebelah kiri wajahnya basah.”“Mungkin kena hujan.”“Mungkin menangis?”“Mana ada batu perempuan menangis, Sayang?”Lelaki itu menjauh membawa putrinya yang berpipi bakpao merah jambu. Meninggalkan sepasang patung batu perempuan, yang membatu karena merana. Dimakan rindu, digerus cinta. Hanya Tuhan yang tahu sudah berapa lama, mungkin seribu tahun lamanya.
Published on February 18, 2015 06:49
Kota Janji
Flash Fiction ini ditulis untuk mengikuti program #FF2in1 dari Tiket.com dan nulisbuku.com #TiketBaliGratis.
oleh: Anggun Prameswari
Tersebutlah sebuah kota; Kota Janji. Di sana, takkan kautemukan bangunan-bangunan menjulang mencakar langit. Atau jalan-jalan beton melintang pukang. Di Kota Janji, yang bisa kautemui hanyalah harapan-harapan yang bertumbuhan, mekar, mengayun-ayun ditiup angin. Harapan yang lahir dari percintaan janji dengan waktu. Dan di sanalah aku memutuskan, di Kota Janji, kita akan bertemu.Keningmu berkerut saat tahu kita akan melepas rindu di Kota Janji, yang seperti namanya, akan menjanjikan harapan-harapan yang mengembang wangi, persis adonan roti di tungku bakar. “Di Kota Janji selalu senja sepanjang hari. Langitnya merah. Semburatnya kuning, kadang ungu atau jingga. Di Kota Janji, kita menanam harapan supaya nanti bisa kupetik,” ujarku malu-malu, menyelipkan rambut ke belakang telinga.“Apa harapanmu?” Lengan kami bersinggungan. Kulitnya berkilat cokelat madu. “Kamu.”Dalam debar yang bertubi-tubi, kubiarkan angin menerbangkan rambutku menutupi wajah. Jarimu menyibak, merapikannya kembali. Napas hangat menyapu pipiku. Kini aku tahu, kulitmu lebih mirip dingin embun di tanah bekas hujan. Lembap menelusup bibirku, menggetarkan pundakku. Aku terpejam. Lirih kutangkap suaramu, “maka tanamlah harapan itu, di Kota Janji.”Tepat saat kubuka mata, kau hanya berkata, “Aku harus pergi.” “Kapan kembali?” Kau tak menjawab. “Kalau begitu, biar aku menanam harapan,” ujarku tersenyum. “Nanti kita sama-sama petik saat bertemu.”Kupejamkan mata. Bibirmu mengecupku sekali lagi. Lebih lama, seakan berpesan, bahwa perpisahan ini tak lebih lama dari sebuah ciuman.***Di Kota Janji, kutanam harapan. Kini bibitnya menyeruak, tumbuh meliar, menjalarkan tunas-tunas menjadi kembang. Kukenakan gaun terbaikku. Sebuah gaun bertali spaghetti, berbahan brokat putih, yang kecil di pinggang, berlipit mengembang di bawah. “Aku pasti datang, tapi tidak sekarang. Aku sedang bersamanya,” “Tapi kau selalu bersamanya.”“Karena dia terlalu mencintaiku.”“Menurutmu, aku tidak cukup mencintaimu, sehingga hanya bisa menunggu?”Kurasakan lembar kelopak harapan yang kutanam berguguran.“Cintamu tak pernah kurang,” katamu. “Kadang cinta saja tidak cukup.”“Cintaku cukup,” ujarku. “Kau yang selalu merasa kurang.”***Kau adalah harapan yang kutanam di Kota Janji. Namun, di Kota Janji tak selalu senja sepanjang hari. Ada kalanya akan turun malam-malam yang gelap. Saat harapan yang ditanam berguguran, maka malam akan datang. Langit akan terlalu pekat untuk ditembus cahaya. Bukankah seperti itulah hidup, gelap bila harapan ternyata padam, pekat tak ternoda?Aku tahu betul, di Kota Janji, pantang menangis. Bila ada air mata yang tumpah, artinya ada harapan yang telah patah. Tapi aku telanjur menangis. Di bulirnya, tersimpan rindu yang lama kutabung, untuk suatu hari kuhamburkan di pelukmu.Malam turun makin cepat. Kelamnya mengganti merah senja. Aku memeluk diri sendiri yang menggigil kesepian. Kulihat harapan yang pernah kutanam, perlahan menguncup, layu, merunduk menyambut malam.Kelak, aku akan datang ke Kota Janji, bisikmu diantarkan angin. Kapan?Kau membisu. Air mataku meluncur lagi ke pucuk rerumputan yang menyapu telapak kakiku. Kujumput sisa harapan. Kutanam sekali lagi. Seperti hukum di Kota Janji, saat harapan kembali ditanam, maka hari kembali senja. Di langit muncul warna jingga seperti titik noda, meluas, hingga senja datang sepenuhnya.Maka kau tetap kutunggu di Kota Janji, kembali kutangkupkan tangan di atas paha. Kuatur gaunku hingga menutupi dudukan bangku panjang. Kubiarkan kakiku mengayun tak terbalut apapun. Aku terus menunggumu di Kota Janji, yang selalu senja sepanjang hari.***
Published on February 18, 2015 06:23
November 4, 2014
Yang Terbaring di Dasar Danau
Muat di Harian Tribun Jabar, Minggu, 2 November 2014

Tahukah kau, ada yang terbaring di dasar danau. Seorang perempuan cantik, terlalu memesona sampai bidadari-bidadari di langit menundukkan kesombongannya. Entah sejak kapan dia berbaring di sana, di dasar danau yang permukaannya selalu tenang. Konon hatinya ditikam belati. Bukan belati biasa, melainkan ditempa dari kesepian panjang. Kesepian yang lahir dari pedihnya ditinggalkan.Matamu membulat. Setengah percaya. Selebihnya meremehkan. Wanita di hadapanmu terlalu banyak membual untuk ukuran orang yang baru dikenal. Kalian sedang berdiri di pinggir danau yang permukaannya lebih tenang dari ekspresi wajahmu yang selalu datar.Tidak bisakah wanita ini menceritakan kisahnya pada orang lain saja?Ujung gaunnya meliuk diterbangkan angin. Kau bisa melihat sepasang paha ramping seputih susu. Di kepalamu, pertama yang terlintas adalah bagaimana raut wajah perempuan itu, jika kau menyentuh sisi paha dalamnya, sekaligus mengecupnya.Perempuan yang terbaring di dasar danau itu tahu, hati siapa saja yang dirundung kesepian. Kau tahu, kesepian bisa menajamkan telinga? Telinga seperti itulah yang bisa mendengarkan nyanyiannya.Kau melemparkan pandangan ke danau. Diam-diam kaucoba menajamkan telinga. Apa benar ada suara perempuan bernyanyi, mengalun dari balik permukaan danau? Yang tertangkap inderanya hanya gemerisik angin, suara daun berjatuhan, dan irama napas wanita di sampingmu. Bagus, batinmu. Baru bertemu, sudah jadi pembohong.Namun, hati-hati. Mendengarnya sekali, kau akan bersuka cita. Kedua kalinya, hatimu akan terpilin, diingatkan kembali akan kesunyian. Makin kau mendengarnya, makin kau tak bisa melupakannya. Terikat, tak bisa berpisah dengan yang terbaring di dasar permukaan danau; yang sesungguhnya tak kalah kesepiannya denganmu.Kau menghela napas. Wanita ini harus dihentikan. Dengan wajah tak peduli, kau memanggul softcasegitar mendahuluinya ke mobil. Entah ide gila siapa yang memasangkanmu dengan wanita itu. Namun, pementasan segera digelar dan kalian harus berlatih. Dia penyanyi, kau mengiringinya dengan gitar. Sebatas itulah hubungan kalian. Namun, saat matamu tertumbuk pada selingkar cincin di jari manisnya, pikiranmu tak bisa lagi kau kendalikan. Ada wanita-wanita yang tak boleh kaucintai. Semacam buah khuldi yang sengaja diciptakan untuk menguji hati. Wanita itu tersenyum. Senyum itu pun telah beranak pinak di benakmu, cepat persis infeksi virus, tahu-tahu malam nanti, kau memimpikannya.Semua orang memanggilnya Senandung. Dan di atas panggung itu, kau memangku gitarmu. Guyuran lampu sorot melimpah menghujani Senandung. Kau hanya seorang pendenting gitar; pendamping biduanita yang menjadi pusat semesta sebenarnya. Tepat pada detik dia melantunkan dendangnya, kau terbius. Ada perasaan girang, bahagia, rindu, pengharapan; mendesak-desak. Membuncah. Terlebih saat sesekali, matanya yang sayu ditembakkan ke arahmu. Jarimu di atas dawai gitar makin menggila, menyesuaikan nada merdunya. Mata kalian bertautan, persis sorot proyektor yang memutarkan film di benak masing-masing. Sejak itu, kalianlah bintang kisah roman kalian sendiri.
***
Sesungguhnya kau sudah melupakan dongeng perempuan yang terbaring di dasar danau. Namun, selayaknya wanita itu pandai membuatmu tergila-gila; padahal kau terbiasa membuat perempuan-perempuan mabuk oleh kecup peluk dan rayu--dia lihai mengingatkanmu kembali pada kisah itu.Pagi itu kau dapati dia tercenung. Tangannya mencengkeram tirai putih yang jendelanya menebarkan pandangan ke arah danau. Dia mengenakan kemeja putihmu; kebesaran nyaris mencapai setengah pahanya. Kau bertanya-tanya, apa kemeja itu masih menyimpang aroma peluk kalian semalam. Pula, apa yang menunggumu jika satu demi satu kancingnya kau lepaskan.Kau hanya telentang dengan kepala tertopang lengan, memandanginya. Dia menoleh. Hatimu mencelus, mendapati sepasang matanya yang digeluti duka. Seperti apa sepi yang menemani perempuan yang terbaring di dasar danau itu? Pagi ini, aku mendengar nyanyiannya. Apa artinya telingaku menajam karena sepi?Kau bangkit lalu memeluknya dari belakang. Kau hirup dalam-dalam aroma yang menguar dari tengkuknya. “Bicara apa kau ini? Ada aku. Bagaimana kau bisa kesepian?”Aku selalu membayangkan dada perempuan di dasar danau itu mengeras ditancap belati. Seperti dadaku kini. Beku oleh sepi, keras oleh sunyi. Dan pagi ini aku dibangunkan oleh lantunan suaranya.Bahkan detik itu juga, kau masih belum menganggapnya gila. Kau memandanginya dengan limpahan kasih, memagut bibirnya yang dingin.“Ada aku yang mencintaimu. Masih kurang apalagi?”Bagaimana kalau kau meninggalkanku? Kau lelaki pemuja kebebasan. Tak ada satu peluk perempuan pun yang sanggup mengikatmu. Belum lagi aku wanita dengan naluri merawat, itu akan membuatmu sesak suatu hari.Mungkin harus ada yang menamparmu. Memberitahumu, bahwa kali ini kau jatuh cinta pada wanita berisi kepala rumit. Belum lagi aku wanita dengan rumah untuk pulang. Bagaimana jika suatu hari aku yang akan meninggalkanmu? Kau akan berkubang dalam kesepian. Telingamu akan tajam karena duniamu terlalu sunyi. Kau akan mendengar nyanyian perempuan yang terbaring di dasar danau itu. Dia akan memintamu mengiringinya bernyanyi. Kau melonggarkan pelukan dan membalikkan tubuhnya. Baru kali ini kau mendapati matanya yang sesungguhnya terbuat dari kristal. Dekapanmu kali ini lebih erat. Benar, sayup-sayup kau mendengar ada yang bernyanyi di kejauhan. Jauh sekali, rasa-rasanya seperti berasal dari dasar danau.
***
Kini kau dan dia berdiri berdampingan di susuran setapak di pinggir danau. Kalian tak berani saling menatap. Ada yang runcing hendak menancapi bola matanya. Siap meledak. Kau bisa dengar yang sekarang kudengar? Kadang aku bertanya, lelaki mana yang tega menancapkan belati kesunyian di dadanya. Jika mencintai ternyata menyakitinya sedemikian rupa, apakah lebih baik sedari awal mematikan rasa? Kau tak menjawab. Matamu lurus menatap bola matanya bergulung-gulung persis mendung yang nyaris pecah jadi hujan. Selama ini, kau mengenal perempuan sebagai taklukan. Kau bertemu, bermanis kata dengan bius mata, bercinta tanpa melibatkan hati, dan berlalu begitu saja keesokan pagi. Wanita ini berbeda. Selalu memperumit segalanya. Bahkan sampai hatimu tak lagi sanggup mengikutinya. Namun, bukankah hati memang tak sesederhana persamaan matematika?“Kita masih bisa saling mencintai dan bersama,” katamu. “Walaupun aku pemuja kebebasan dan kau wanita yang mempunyai rumah untuk pulang.”Cinta apa yang seperti itu? Kita bisa saja bercinta berkali-kali, tapi di penghujung hari kita kembali bergelung sepi. Bukan seperti itu cinta yang kucari.“Lalu apa? Kenapa cintamu rumit sekali?” kau setengah membentak.Kau sederhana. Aku rumit. Itulah yang membuat kita tak saling memiliki. Itulah kenapa aku sering merasa kosong, bila bersamamu. Dan telingaku sudah lelah mendengar nyanyian perempuan yang terbaring di dasar danau. Lama mereka bertatapan. Dalam tarikan napas kesekian, dia menghambur ke pelukmu. Kau menariknya seperti kubangan pasir isap. Pada bibir yang saling bersentuhan, kalian menuliskan kenangan. Kau melihatnya memagutmu dengan mata terpejam dan air mata berlinangan. Tepat saat dia menarik bibirnya lepas, ada retak di dadamu. Sebuah belati dia tikamkan di sana. Untuk pertama kalinya, bukan sayup-sayup lagi, kau kini jelas mendengar suara merdu itu. Rasa-rasanya seperti dari dasar danau di hadapanmu. Jadi perempuan yang terbaring di dasar danau itu benar ada?
***
Entah sudah pagi ke berapa kau mendapati dirimu berdiri di sini. Mencengkeram susuran pembatas danau dan jalan setapak. Malam-malam sebelumnya kau terjaga. Sepertinya wanita itu pergi dengan membawa kantukmu. Kauhabiskan waktu menulis banyak lagu. Ratusan lirik. Seakan kepalamu adalah sumur yang terus meluapkan lumpur. Orang-orang bilang kau patah hati. Namun, kau tahu betul, hatimu tak sekadar patah. Hatimu jatuh pecah. Kepingnya berhamburan, terserak angin ke segala arah.Kau dipeluk kesepian yang tak kau ketahui di mana ujungnya. Benar, kesepian menajamkan telinga. Kau pun mulai menangkap lantunan merdu dari kejauhan. Sangat jauh, seakan berasal dari dasar danau.Lama-lama suara itu nyata. Seakan asalnya dari hatimu sendiri. Mungkin sesungguhnya hatimu dan danau itu serupa. Di dasarnya sama-sama didiami oleh seseorang yang terbaring dengan luka tikam di dada. Di danau, ada perempuan itu. Di hatimu, ada kau sendiri.Kau mulai melangkah. Mengawang tak bisa kau kendalikan. Kau menuruni ujung susuran yang tersambung ke arah pinggir danau. Suara itu tak kasat mata. Tapi kau bisa merasakan ada jerat yang membungkus tubuhmu. Mungkin ketimbang sepi sendiri, kau merasa lebih baik sepi berbagi. Tak kau pedulikan lagi basah yang makin menyergap. Danau itu perlahan merentangkan tangannya. Menawarkan pelukan. Menelanmu pelan-pelan. Tepat saat kau tak tersentuh udara lagi, kau bertekad untuk mengiringi perempuan yang terbaring di dasar danau itu dengan denting gitarmu. Karena kau tahu, kesepian lebih baik bila dibagi.
***
Ada sepasang muda-mudi berangkulan. Keduanya terbius menatap lembayung yang berhamburan di langit. Sang pemuda menoleh ke arah gadisnya. Ada yang tergenapi dalam hatinya saat melihat senyum mengembang di bibir ranum itu.“Kau tahu mitos di danau ini?” tanya gadis itu menoleh cepat.“Siapa yang tidak tahu? Kalau ada sepasang kekasih kemari, maka hubungan mereka akan kandas. Karena kutukan perempuan yang terbaring di dasar danau.”“Banyak juga yang bunuh diri di sini karena patah hati,” sambung si gadis menatap kekasihnya lekat. “Kalau aku meninggalkanmu, apa kamu akan bunuh diri?”“Kamu sendiri?”Keduanya melemparkan pandangan ke arah permukaan danau yang tenang. Benak mereka penuh oleh banyak hal. Riuh oleh gelora cinta yang teredam oleh sekadar genggaman tangan.Tanpa mereka sadari, sayup-sayup terdengar lantunan suara. Seakan berasal dari tempat di kejauhan, tapi juga dekat. Mungkin dari dasar danau; atau dari dasar hati, tempat segala kesunyian bermuara.***
Published on November 04, 2014 21:46
Anggun Prameswari's Blog
- Anggun Prameswari's profile
- 55 followers
Anggun Prameswari isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



